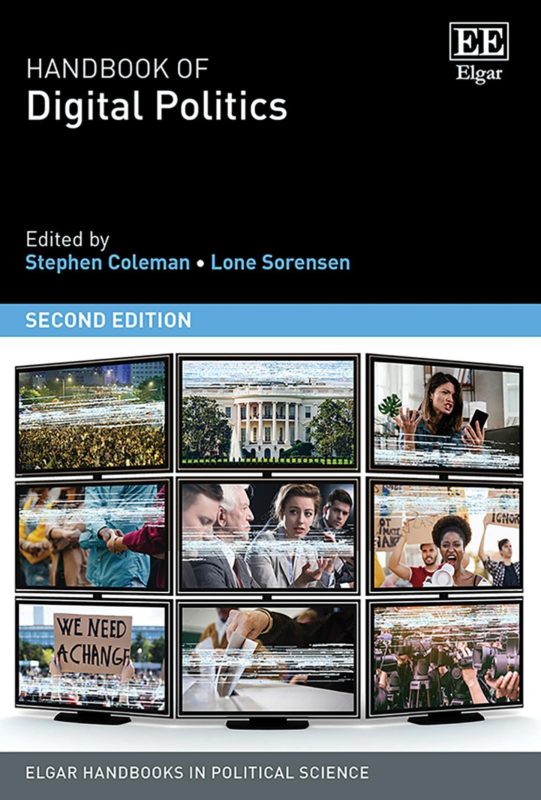
SURABAYA, CAKRAWARTA.com – Dalam satu dekade terakhir, politik digital menjelma menjadi arena paling dinamis dalam sejarah demokrasi modern. Ia bukan lagi sekadar soal bagaimana politisi berkampanye di media sosial, melainkan bagaimana algoritma, platform, dan partisipasi daring membentuk ulang struktur kekuasaan dan relasi antara warga dengan negara. Buku Handbook of Digital Politics (Second Edition) yang disunting oleh Stephen Coleman dan Lone Sorensen (Edward Elgar Publishing, 2023) hadir sebagai semacam “peta besar” untuk memahami transformasi itu yang terlihat begitu kompleks, lintas disiplin, dan menolak kesimpulan tunggal.
Buku ini terdiri dari enam bagian besar dengan 30 bab yang ditulis oleh lebih dari empat puluh pakar dari berbagai universitas ternama dunia. Dari Leeds hingga Lund, dari Michigan hingga Oxford, para kontributor menelisik wajah politik yang kian digital, mulai dari retorika dan citra visual politik daring, kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan publik, hingga populisme dan jurnalisme di era post truth.
Dalam pengantarnya, Coleman dan Sorensen mengingatkan bahwa kajian tentang politik digital sering terjebak dalam dua kubu besar yaitu cyber optimism dan cyber pessimism. Sebagian pihak percaya bahwa internet adalah alat pembebasan demokratis, sementara yang lain menuduhnya memperkuat otoritarianisme dan manipulasi massa.
Coleman dan Sorensen menawarkan jalan ketiga yaitu apa yang kemudian disebut sebagai ambivalensi kreatif. Mereka mengajak pembaca melihat digitalisasi politik bukan sebagai penyelamat atau perusak, melainkan sebagai medan yang penuh tarik-ulur antara kebebasan dan kontrol, antara inovasi dan regulasi.
Bab pertama, A Rhetoric of Digital Politics, menjadi semacam manifesto intelektual. Melalui kisah nyata seperti kudeta Myanmar 2021 dan kepemimpinan digital Volodymyr Zelenskyy di Ukraina, para penulis menunjukkan betapa teknologi dapat berperan ganda yakni alat mobilisasi rakyat sekaligus medium represi. Facebook, Twitter (sekarang X), dan WhatsApp bukan sekadar saluran komunikasi, tetapi infrastruktur kekuasaan yang bisa diambil alih siapa saja, mulai dari aktivis hingga diktator.
Ambivalensi ini menuntut pembacaan baru atas demokrasi digital. “Kita hidup di masa ketika politik bukan hanya bertarung soal ide, tetapi juga tentang siapa yang berhak mendefinisikan pengalaman dan emosi,” tulis Coleman. Politik hari ini, lanjutnya, adalah politik afektif yaitu politik yang memobilisasi rasa takut, marah, atau bangga melalui algoritma yang tak kasatmata.
Salah satu kekuatan buku ini adalah usaha sadar untuk “de-Westernisasi” studi politik digital. Bab kedua, De-Westernizing Digital Politics: A Global South Viewpoint karya Bruce Mutsvairo dan rekan-rekannya, menjadi pengingat penting bahwa pengalaman politik digital di Afrika, Asia, dan Amerika Latin tak bisa dibaca dengan kacamata Barat.
Di banyak negara Global South, tulis mereka, internet bukan semata ruang deliberasi publik, melainkan juga arena perlawanan terhadap represi dan kemiskinan struktural. Mutsvairo mencontohkan bagaimana pemerintah di Ethiopia, Kamerun, dan Chad kerap mematikan internet ketika protes meningkat. Demokrasi digital di sana bukan soal kebebasan berekspresi, melainkan pertarungan eksistensial antara negara dan warganya.
Bab ini dengan tajam mengkritik kecenderungan teori Barat yang memandang internet sebagai otomatis “demokratis”. Dengan gaya yang lugas, para penulis menunjukkan bahwa algoritma global tetap beroperasi dalam ketimpangan ekonomi-politik yang diwariskan kolonialisme. Di sinilah “politik digital” menjadi lanjutan dari sejarah panjang ketidakadilan global, hanya saja kali ini berlangsung di server, bukan di jalanan.
Bagian ketiga buku ini menyoroti bagaimana teknologi membentuk politik, bukan hanya sebagai alat, tetapi sebagai aktor. Heather Ford menulis tentang “keber-peristiwa-an data” yaitu bagaimana peristiwa politik diciptakan, disusun, dan dimaknai lewat data yang terus mengalir. Ulrike Klinger membedah kekuatan algoritma yang secara halus menggeser arah opini publik, sementara Leah Henrickson menyoroti artificial intelligence atau akal imitasi (AI) dalam politik, dari chatbot partai hingga analisis sentimen pemilih.
Ada juga bab yang menelusuri bagaimana arsitektur platform seperti Facebook, Instagram, dan TikTok membentuk partisipasi politik. Michael Bossetta menyebutnya sebagai platform-first approach yang bahwa desain dan logika bisnis platform jauh lebih menentukan perilaku politik daring ketimbang ideologi penggunanya.
Temuan ini relevan untuk konteks Indonesia, di mana politik elektoral semakin didorong oleh “politik klik” dan buzzer. Buku ini memberi landasan akademik bagi siapa pun yang ingin memahami mengapa algoritma kadang lebih kuat daripada ideologi, dan mengapa viralitas bisa lebih menentukan nasib politisi daripada tentang visi sang politisi.
Bagian kelima dan keenam mengupas dua pilar klasik demokrasi yaitu partai politik dan media. Thomas Wellings dan Lone Sorensen menulis tentang digital performance of populism yaitu bagaimana pemimpin populis memanfaatkan gaya personal, kemarahan publik, dan media sosial untuk membangun kesan “otentik”. Dari Trump hingga Bolsonaro, performa digital menjadi modal politik baru yang melampaui ideologi.
Sementara itu, bagian terakhir membedah dunia jurnalisme digital yang kian kabur batasnya. Bab tentang fake news oleh Bente Kalsnes dan right-wing alternative media oleh Kristoffer Holt memperlihatkan bagaimana informasi palsu bukan hanya gangguan, melainkan ekosistem baru dengan logika ekonomi tersendiri.
Michael Xenos menutup buku ini dengan refleksi menarik bahwa banyak warga kini mengonsumsi politik bukan lewat berita serius, tetapi lewat infotainment yakni kombinasi hiburan dan politik yang mempermainkan emosi sekaligus mengaburkan fakta. Sebuah fenomena yang juga nyata dalam lanskap media Indonesia.
Sebagai buku akademik, Handbook of Digital Politics bukan bacaan ringan. Namun gaya penyuntingan Coleman dan Sorensen membuatnya tetap hidup dan mudah diikuti. Mereka tidak memaksakan kesimpulan tunggal, melainkan menyajikan mozaik pemikiran yang saling melengkapi yang kadang berlawanan, tapi justru di sanalah kekuatannya.
Buku ini penting bukan hanya bagi akademisi komunikasi politik, tetapi juga bagi jurnalis, aktivis, dan pembuat kebijakan yang berhadapan langsung dengan arus deras disinformasi dan politik algoritmik. Ia mengajarkan bahwa demokrasi digital tak bisa hanya diukur dari jumlah like atau retweet, melainkan dari kemampuan masyarakat untuk memahami ambivalensi di balik setiap klik.
Di tengah dunia yang makin terhubung sekaligus terpecah, Handbook of Digital Politics adalah pengingat bahwa teknologi tidak pernah netral. Ia bisa menjadi jembatan, bisa pula menjadi jerat. Dan di antara keduanya, manusia tetap harus belajar menjadi subjek, bukan sekadar data. Semoga.
Data Buku:
Judul: Handbook of Digital Politics (Second Edition)
Editor: Stephen Coleman & Lone Sorensen
Penerbit: Edward Elgar Publishing
- Tahun Terbit: 2023
Tebal: 472 halaman



