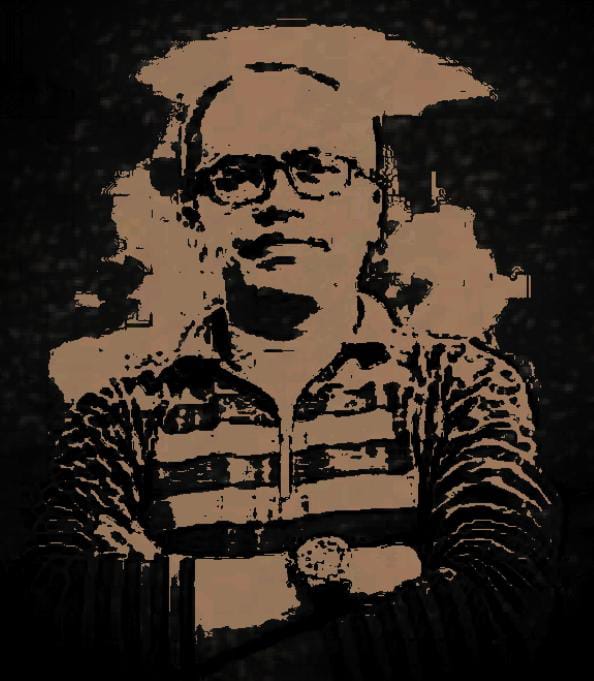
Keadaan darurat adalah salah satu keputusan yang paling sulit bagi pemerintah mana pun, karena berdampak langsung pada stabilitas negara dan kebebasan warga negara. Dari pengalaman berbagai negara, termasuk Korea Selatan dan Indonesia, keadaan darurat sering kali memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana melindungi negara tanpa mengorbankan demokrasi dan hak asasi manusia?
Baru-baru ini, pada 3 Desember 2024, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengejutkan dunia dengan mendeklarasikan darurat militer menyusul situasi ketegangan politik yang meningkat. Langkah ini mencakup pembatasan kebebasan pers, pelarangan demonstrasi, dan pembubaran sementara Majelis Nasional. Meski pemerintah berdalih menjaga stabilitas, kebijakan ini memunculkan kecemasan akan kembalinya otoritarianisme di negara yang telah berjuang untuk demokrasi sejak 1987.
Deklarasi ini membawa ingatan publik Korea Selatan kembali ke era kelam otoritarianisme. Di bawah pemerintahan Park Chung Hee (1961–1979) dan Chun Doo Hwan (1979–1988), darurat militer sering digunakan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan. Kebijakan seperti pembubaran parlemen, pembatasan kebebasan berbicara, dan penindasan brutal terhadap oposisi menjadi ciri khas masa itu. Peristiwa pembantaian Gwangju pada 1980, di mana ribuan warga tewas akibat penindasan militer, menjadi salah satu simbol paling kelam dari era tersebut.
Setelah perjuangan panjang menuju demokrasi pada 1987, sistem demokrasi Korea Selatan dibangun dengan susah payah, sehingga setiap ancaman terhadap prinsip demokrasi—seperti deklarasi darurat militer baru-baru ini—memicu reaksi keras.
Namun, yang membuat peristiwa ini luar biasa adalah keberanian Majelis Nasional Korea Selatan dalam merespons. Dalam waktu kurang dari 24 jam, parlemen mencabut keputusan darurat militer melalui mosi khusus. Dukungan kuat dari masyarakat sipil, akademisi, dan media independen turut menjadi faktor penentu dalam mengakhiri kebijakan yang dianggap merusak prinsip-prinsip demokrasi tersebut.
Pengalaman ini memberikan pelajaran penting tentang peran pengawasan parlemen dan partisipasi publik dalam membatasi kekuasaan eksekutif, bahkan dalam situasi genting.
Sejarah Penerapan Keadaan Darurat di Indonesia
Indonesia memiliki sejarah panjang terkait keadaan darurat, yang sering kali menjadi alat legitimasi kekuasaan untuk menekan oposisi atau memaksakan kebijakan tertentu. Salah satu contoh paling kontroversial adalah darurat militer di Aceh pada 2003.
Pada masa itu, Presiden Megawati Soekarnoputri menetapkan darurat militer untuk menghadapi konflik bersenjata dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Langkah ini diambil dengan dasar Perppu Nomor 23 Tahun 1959, yang memberi wewenang luas kepada TNI untuk mengontrol wilayah. Meski pemerintah mengklaim kebijakan tersebut berhasil meredam pemberontakan, harga yang harus dibayar sangat mahal: korban sipil yang tinggi, pelanggaran HAM, dan trauma kolektif bagi masyarakat Aceh.
Pengalaman ini menyoroti risiko besar jika keadaan darurat tidak diatur dengan mekanisme pengawasan yang kuat. Regulasi seperti Perppu Nomor 23 Tahun 1959 yang diadopsi dari era otoriter tetap digunakan bahkan di era reformasi.
Upaya menggantinya melalui rancangan undang-undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU PKB) pada 1999 dan 2019 selalu menghadapi penolakan keras karena dianggap terlalu represif. Pada 2019, misalnya, usulan RUU PKB menuai kritik luas karena dianggap tidak sesuai dengan semangat reformasi dan melanggar hak-hak konstitusional warga. Meskipun akhirnya pembahasan RUU ini dihentikan, fakta bahwa pemerintah terus mencoba menghidupkan regulasi serupa menunjukkan pentingnya kewaspadaan publik terhadap potensi abuse of power.
Pilar Demokrasi di Tengah Keadaan Darurat
Darurat militer yang baru saja terjadi di Korea Selatan menunjukkan bahwa demokrasi dapat bertahan bahkan di tengah situasi genting. Indonesia dapat mengambil pelajaran penting dari bagaimana Korea Selatan menghadapi situasi ini dengan memastikan prinsip-prinsip checks and balances berjalan. Parlemen Korea Selatan yang dengan cepat mencabut keputusan darurat militer membuktikan pentingnya peran legislatif dalam menjaga batas-batas kekuasaan eksekutif.
Partisipasi publik juga menjadi kunci. Tekanan dari masyarakat sipil, akademisi, dan media independen memberikan legitimasi kuat terhadap pembatalan kebijakan yang dinilai merugikan demokrasi tersebut. Selain itu, transparansi dalam pengambilan keputusan menciptakan ruang diskusi yang sehat dan mencegah tindakan represif yang berpotensi merugikan rakyat.
Indonesia perlu mereformasi regulasi keadaan darurat agar lebih demokratis. Regulasi yang ada saat ini harus dibatasi secara jelas dalam hal durasi, ruang lingkup, dan mekanisme evaluasi. Selain itu, pelibatan lembaga yudikatif sebagai pengawas independen harus diperkuat untuk meninjau legalitas keputusan darurat.
Keputusan-keputusan selama keadaan darurat harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan politik. Akuntabilitas menjadi aspek penting dalam memastikan kebijakan yang diambil tidak melanggar hak asasi manusia. Setiap pelanggaran, terutama yang melibatkan kekerasan, harus diusut tuntas dan ditindak sesuai hukum yang berlaku.
Keamanan dan Kebebasan yang Berimbang
Peristiwa darurat militer di Korea Selatan pada awal Desember 2024 mengingatkan kita bahwa demokrasi yang kuat adalah demokrasi yang mampu bertahan di tengah situasi krisis. Transparansi, checks and balances, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk menjaga agar kebijakan keadaan darurat tidak berubah menjadi alat penindasan.
Indonesia, dengan sejarah panjangnya, harus belajar dari pengalaman ini. Regulasi keadaan darurat yang represif seperti Perppu Nomor 23 Tahun 1959 dan usulan RUU PKB perlu digantikan dengan kerangka hukum yang lebih demokratis, transparan, dan melibatkan semua pemangku kepentingan.
Sebagai bangsa yang telah melalui berbagai ujian demokrasi, saatnya Indonesia menunjukkan bahwa keamanan dan hak asasi manusia bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Dengan reformasi yang tepat, regulasi keadaan darurat dapat menjadi instrumen untuk melindungi negara tanpa mengorbankan kebebasan warganya.
KHAIRUL FAHMI
Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS)



