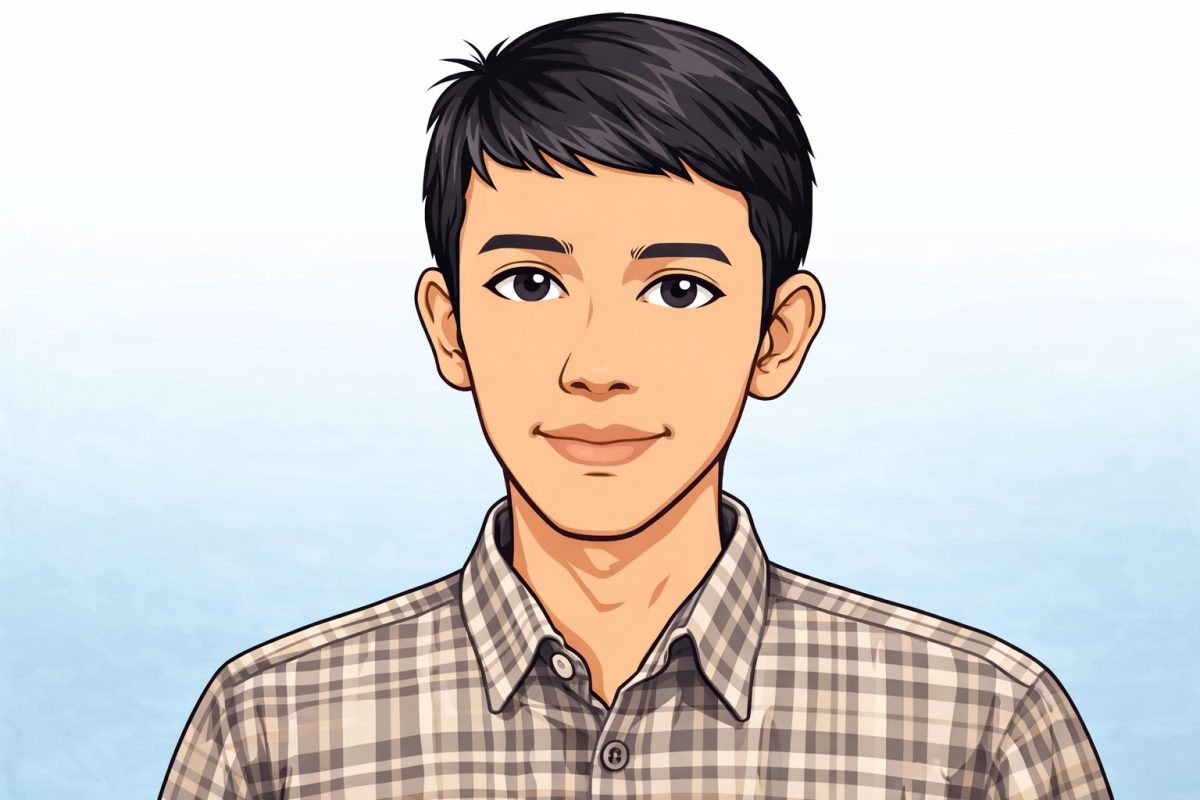
Serangan militer Amerika Serikat ke Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro pada Sabtu (3/1/2026), menandai perubahan serius dalam praktik politik global. Atas nama pemberantasan narkoterorisme, Washington melakukan operasi lintas batas, menangkap kepala negara berdaulat, dan memaksakan proses hukum domestik tanpa mandat multilateral yang sah. Langkah ini secara terang menabrak prinsip dasar hukum internasional, khususnya larangan penggunaan kekuatan terhadap kedaulatan negara lain.
Kasus Venezuela tidak bisa dibaca sebagai insiden terpisah atau sekadar respons keamanan. Ia menunjukkan bagaimana hukum internasional kini diperlakukan secara selektif: mengikat negara lemah, tetapi dapat disisihkan oleh negara kuat ketika kepentingan strategis dipertaruhkan. Dalam situasi ini, unilateralisme bukan lagi penyimpangan, melainkan metode yang dinormalisasi.
Di balik narasi terorisme, terdapat fakta geoekonomi yang menentukan arah kebijakan ketika Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia sebesar 300 miliar barel. Dalam konteks krisis energi global dan meningkatnya rivalitas kekuatan besar, sumber daya energi kembali menjadi variabel utama dalam kalkulasi geopolitik. Ketika energi menjadi kepentingan, kedaulatan berubah menjadi variabel tawar-menawar.
Tulisan ini berpijak pada satu argumen tegas, Venezuela adalah contoh bagaimana politik global bergerak menuju barbarisme kontemporer, di mana kekuasaan dibungkus hukum dan moralitas, sementara prinsip kedaulatan dikorbankan demi kepentingan material. Bukan hanya nasib satu negara yang dipertaruhkan, melainkan kredibilitas tatanan internasional yang selama ini terkonstruksi.
Minyak dan Logika Materialisme Global
Dalam politik global kontemporer, minyak telah menjadi simbol paling telanjang dari materialisme kekuasaan modern. Ia bukan sekadar komoditas energi, melainkan penentu posisi, perlakuan, dan nasib sebuah negara. Venezuela, dengan cadangan minyak terbesar di dunia, menempati posisi paradoks ketika suatu negara kaya akan sumber daya namun memiliki posisi rentan secara politik yang menjadikan daya tarik sekaligus kutukan.
Dunia modern mewarisi logika lama yang tidak pernah benar-benar ditinggalkan di mana sumber daya melahirkan kekuasaan, kekuasaan menuntut legitimasi. Dalam logika ini, legitimasi tidak lagi bersumber dari hukum atau etika, melainkan dari kemampuan menguasai dan mengamankan kepentingan material. Ketika energi menjadi pusat orientasi, nilai kemanusiaan dan kedaulatan dengan mudah disisihkan sebagai hambatan teknis.
Minyak lalu berfungsi sebagai alat seleksi global. Negara yang sejalan dengan kepentingan penguasa energi akan diperlakukan sebagai mitra. Negara yang menolak atau mengganggu arus kepentingan tersebut akan dilabeli sebagai ancaman, rezim bermasalah, atau sumber instabilitas. Normalitas hidup suatu bangsa tidak lagi ditentukan oleh hak berdaulatnya, melainkan oleh posisinya dalam rantai kepentingan energi global.
Dalam kerangka ini, intervensi tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran, tetapi sebagai koreksi. Kekerasan politik diterima sebagai mekanisme pengaturan. Minyak bukan hanya menentukan siapa yang berkuasa, tetapi juga siapa yang boleh hidup normal dan siapa yang dianggap layak dikorbankan demi stabilitas versi kekuatan besar.
Hukum, Moralitas, dan Kemunafikan Global
Hukum internasional hari ini semakin kehilangan makna etiknya. Ia bekerja tidak sebagai norma yang setara, melainkan sebagai mekanisme selektif yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Negara lemah dituntut patuh pada prinsip kedaulatan dan non-agresi, sementara negara kuat dengan mudah menafsirkan ulang, menangguhkan, atau mengabaikannya ketika kepentingannya terganggu. Dalam kondisi ini, hukum tidak lagi menjadi pembatas kekuasaan, tetapi justru pelumas bagi praktik dominasi.
Bahasa moral kemudian digunakan untuk menutup celah legitimasi. Terorisme, narkotika, dan demokrasi tampil sebagai kata kunci yang ampuh. Ia sederhana, emosional, dan mudah diterima publik. Namun di balik retorika tersebut, yang bekerja bukan penegakan nilai, melainkan moral instrumental yakni benar jika menguntungkan, salah jika merugikan. Dunia Barat maupun Timur sama-sama terjebak dalam logika ini. Prinsip tidak lagi berdiri sendiri, melainkan tunduk pada kalkulasi kepentingan.
Dalam kerangka tersebut, Venezuela tidak diperlakukan sebagai negara berdaulat, melainkan sebagai “masalah” yang harus dibereskan. Kompleksitas sosial, politik, dan historisnya disederhanakan menjadi ancaman keamanan. Ketika sebuah negara direduksi menjadi objek masalah, maka intervensi, sanksi, bahkan kriminalisasi politik dapat dibenarkan tanpa rasa bersalah. Di titik inilah hukum mengalami degradasi paling serius. Ia tidak lagi berfungsi sebagai norma bersama yang melindungi semua, tetapi berubah menjadi alat kekuasaan yang digunakan untuk menertibkan yang lemah dan membebaskan yang kuat.
Barbarisme Kontemporer dan Ingatan Global South
Barbarisme dalam politik global hari ini tidak lagi tampil sebagai penaklukan kasar dengan pendudukan wilayah dan bendera perang. Ia hadir lebih rapi dan prosedural melalui sanksi ekonomi, kriminalisasi politik, serta intervensi yang dibungkus bahasa hukum. Kekerasan tidak selalu meledak, tetapi bekerja perlahan dan sistematis, menghancurkan kapasitas negara sekaligus melumpuhkan daya hidup masyarakatnya. Inilah wajah baru barbarisme yang diterima sebagai praktik normal.
Dalam skema ini, Global South kembali menjadi ladang eksperimen kekuasaan. Negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin diperlakukan sebagai ruang uji coba bagi sanksi, tekanan, dan rekayasa politik. Pengalaman kolonial yang seharusnya menjadi pelajaran justru diulang dalam bentuk baru. Kontrol tidak lagi dijalankan melalui kolonialisme formal, melainkan lewat ketergantungan ekonomi, delegitimasi politik, dan penundukan hukum.
Kedaulatan pun mengalami degradasi makna. Ia tidak lagi dipahami sebagai hak melekat suatu bangsa, melainkan sebagai izin sementara yang dapat dicabut ketika kepentingan kekuatan besar terganggu. Negara dianggap berdaulat sejauh patuh, dan menjadi sasaran ketika membangkang. Dalam kondisi ini, prinsip kesetaraan antarnegara kehilangan relevansinya.
Dunia modern memang bergerak maju secara teknologi, tetapi mundur secara etika. Rasionalitas dipisahkan dari nurani, dan kekuasaan dilepaskan dari tanggung jawab moral. Venezuela bukan kasus tunggal, melainkan penanda bahwa politik global sedang berjalan ke arah yang berbahaya. Ketika barbarisme dinormalisasi, yang terancam bukan hanya negara tertentu, tetapi fondasi peradaban internasional itu sendiri.
Indonesia dan Pilihan Moral di Tengah Kekacauan
Di tengah kekacauan tatanan global yang kian telanjang, Indonesia tidak berada di ruang hampa. Bangsa ini lahir dari pengalaman kolonial yang panjang, dari luka penaklukan yang menjadikan kedaulatan bukan konsep abstrak, melainkan nilai hidup. Karena itu, politik luar negeri tidak semestinya dipersempit menjadi soal manuver diplomatik, perluasan jejaring, atau kedekatan dengan kekuatan besar. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah soal posisi moral yakni ketika Indonesia berdiri pada saat kedaulatan diinjak dan hukum dipermainkan.
Prinsip bebas aktif tidak dimaksudkan sebagai tempat berlindung dari sikap. Bebas berarti tidak tunduk pada kepentingan siapa pun, aktif berarti hadir ketika prinsip dilanggar. Ketika dunia bergerak menuju normalisasi intervensi, sanksi kolektif, dan kriminalisasi politik lintas batas, diam bukanlah netralitas. Diam adalah bentuk persetujuan yang paling sunyi. Dalam politik global, ketidaksuaraan sering kali lebih berbahaya daripada keberpihakan yang keliru.
Pesan konstitusi Indonesia jelas dan tidak ambigu bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kalimat itu bukan peninggalan sejarah, melainkan kompas etik. Ia menuntut keberanian untuk menolak barbarisme, meskipun hadir dengan wajah modern dan bahasa moral. Di titik inilah Indonesia diuji. Bukan pada seberapa lihai bergaul dengan semua kekuatan, tetapi pada kesanggupan menjaga nurani di tengah dunia yang semakin kehilangan rasa malu. Jika kedaulatan dibiarkan menjadi variabel kepentingan, maka cepat atau lambat, semua bangsa akan belajar bahwa yang disebut peradaban hanyalah jeda singkat sebelum kekuasaan kembali telanjang. Entahlah. (*)
PROBO DARONO YAKTI
Dosen Hubungan Internasional dan Periset CSGS FISIP UNAIR sekaligus Co-founder Nusantara Policy Lab



