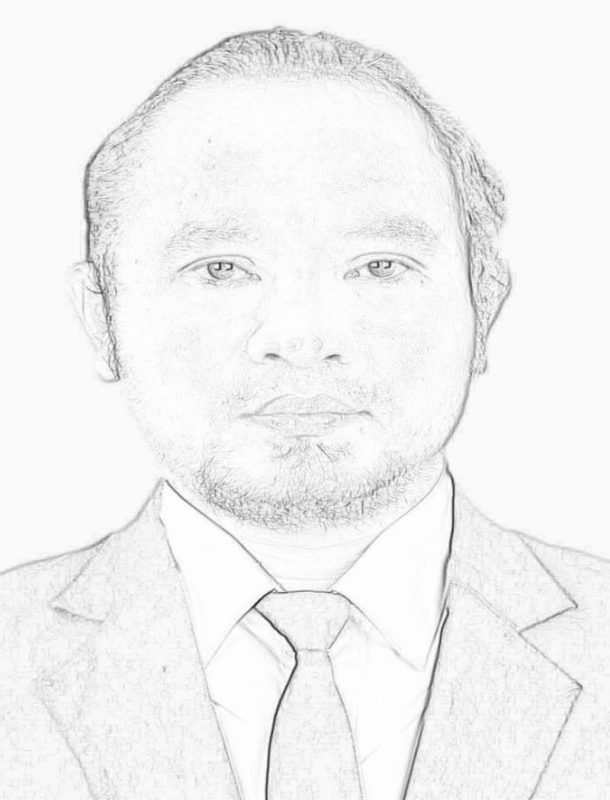Pendidikan selalu menjadi wajah paling jujur dari arah peradaban suatu bangsa. Di Indonesia, wajah itu sering menampakkan paradoks yaitu di tengah jargon pemerataan, ketimpangan justru kian terasa tajam.
Di atas kertas, setiap anak berhak atas pendidikan bermutu. Namun di lapangan, mutu dan akses masih ditentukan oleh alamat rumah, kelas sosial, bahkan status ekonomi orang tua.
Dalam konteks itulah pemerintah memperkenalkan Sekolah Rakyat (SR) yaitu sekolah berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Tujuannya mulia yakni memutus rantai kemiskinan antargenerasi sekaligus memperluas akses pendidikan yang setara.
Namun, sebagaimana setiap kebijakan besar, gagasan ini tak luput dari perdebatan. Sebagian menilai SR sebagai bentuk keberpihakan konkret pada kelompok marjinal. Sebagian lain khawatir, program ini justru mempertegas sekat sosial yaitu menciptakan dua dunia pendidikan yakni satu bagi kelas menengah, satu lagi bagi kaum miskin. Pertanyaan moral pun muncul, apakah Sekolah Rakyat benar-benar jalan menuju keadilan, atau hanya “panggung kebaikan” yang mengulang pola lama?
Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan UNESCO Global Education Monitoring menunjukkan ketimpangan pendidikan Indonesia masih termasuk yang tertinggi di Asia Tenggara. Faktor geografis, sosial, dan ekonomi membuat jutaan anak di perdesaan dan kawasan timur tertinggal dalam literasi dan numerasi.
Program Sekolah Rakyat hadir sebagai respons atas realitas itu. Dengan sistem asrama, anak-anak dari keluarga miskin dapat tinggal dan belajar tanpa harus memikirkan ongkos transportasi, biaya makan, atau fasilitas digital. Negara menanggung semua kebutuhan agar mereka fokus belajar.
Secara rasional, kebijakan ini masuk akal dimana pendidikan dijadikan instrumen utama untuk menekan kemiskinan ekstrem, yang pada 2024 masih menyentuh sekitar 1,2% penduduk. Pemerintah menilai investasi jangka panjang di bidang pendidikan jauh lebih efektif daripada sekadar bantuan tunai.
Gagasan Sekolah Rakyat bukan barang baru. Akar sejarahnya dapat ditelusuri ke pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa (1922). Ia menolak sistem pendidikan kolonial yang elitis dan menindas, dan menekankan pentingnya pendidikan yang “memerdekakan manusia lahir dan batin”.
Setelah Reformasi, muncul beragam inisiatif Sekolah Rakyat dari masyarakat sipil tanpa campur tangan negara. Misalnya, Sekolah Rakyat Petani di Kulon Progo yang berfokus pada kemandirian agraria; Sekolah Rakyat Mataram di Yogyakarta bagi anak-anak pekerja kota; dan Sekolah Rakyat Indonesia di Bandung yang menolak komersialisasi pendidikan dan menumbuhkan empati serta kreativitas. Sekolah-sekolah ini tumbuh dari semangat perlawanan terhadap ketimpangan, bukan dari keputusan administratif. Mereka hadir sebagai bentuk pendidikan yang lebih manusiawi dan berpihak pada rakyat kecil.
Namun potensi besar itu dibayangi sejumlah dilema. Pertama, risiko stigma sosial.
Sosiolog Pierre Bourdieu menyebut pendidikan sebagai arena reproduksi sosial. Jika SR dipersepsikan sebagai “sekolah untuk orang miskin”, maka label itu akan menempel pada siswanya. Alih-alih membuka mobilitas sosial, SR bisa memunculkan labeling effect yakni murid dianggap berbeda, bahkan lebih rendah, dari sekolah umum.
Kedua, soal mutu pengajaran dan kurikulum. Bangunan megah tak berarti banyak tanpa guru yang berkualitas dan berjiwa dialogis. Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed menegaskan bahwa pendidikan sejati menuntut dialog, bukan doktrin. SR akan gagal bila hanya menanamkan disiplin tanpa menumbuhkan kesadaran kritis.
Ketiga, efisiensi fiskal dan keberlanjutan. Model sekolah berasrama menuntut biaya besar dan perencanaan jangka panjang. Tanpa transparansi anggaran dan evaluasi berbasis data, SR bisa berubah menjadi proyek sesaat yang lebih politis daripada edukatif.
Paulo Freire mengingatkan bahwa pendidikan sejati adalah tindakan pembebasan, bukan pengisian pikiran kosong. Guru dan murid seharusnya belajar bersama, membaca realitas sosial, dan mengubahnya. Pemikiran ini sejalan dengan falsafah Ki Hajar Dewantara dimana pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.
Namun dalam praktiknya, banyak Sekolah Rakyat justru terjebak pada sistem lama yang meniru pola sekolah formal tanpa memperhatikan kebutuhan sosial di lingkungannya sendiri.
Dari sisi sosiologis, Sekolah Rakyat dapat dilihat dari tiga dimensi utama yaitu fungsi sosial, struktur sosial, dan mobilitas sosial. Pertama, fungsi sosial pendidikan seharusnya menjadi jalan mobilitas vertikal bagi warga. Namun faktanya, pendidikan sering menjadi alat reproduksi ketimpangan. Kedua, dari sisi struktur sosial, SR berpotensi menciptakan segregasi baru. Pemisahan anak miskin dalam sekolah khusus justru memperlebar jarak sosial. Emile Durkheim pernah mengingatkan, fungsi moral pendidikan adalah menanamkan solidaritas sosial, bukan mempertebal tembok antar kelas. Ketiga, soal mobilitas sosial. Jika SR mampu menumbuhkan habitus baru yaitu percaya diri, nalar kritis, dan kompetensi hidup, maka ia dapat menjadi sarana mobilitas sejati.
Masalah terbesar banyak Sekolah Rakyat adalah keberlanjutan. Banyak yang bergantung pada donasi atau semangat relawan. Ketika dukungan berhenti, aktivitas pun meredup.
Padahal, pendidikan rakyat memerlukan fondasi struktural yang kokoh agar tak bergantung pada belas kasihan.
Tantangan lain adalah stigma sosial. Sebagian masyarakat masih memandang Sekolah Rakyat sebagai “sekolah kelas dua”. Padahal istilah rakyat seharusnya bermakna kebangsaan, bukan kemiskinan. Sekolah Rakyat mesti dipahami sebagai ruang kesetaraan, bukan penampungan bagi mereka yang tersisih.
Agar Sekolah Rakyat benar-benar menjadi instrumen keadilan sosial, setidaknya ada tujuh prinsip yang perlu dipegang:
Ketepatan sasaran. Seleksi siswa berbasis data kemiskinan yang valid dan transparan.
Standar mutu nasional. Kurikulum dan asesmen setara dengan sekolah negeri terbaik.
Guru berkualitas dan dialogis. Pelatihan intensif dalam pedagogi partisipatif mutlak dilakukan.
Akuntabilitas fiskal. Publik berhak tahu biaya per siswa dan dampak sosialnya.
Tanpa stigma. Narasi publik harus menegaskan SR sebagai simbol prestasi, bukan belas kasihan.
Keterlibatan komunitas. Orang tua dan masyarakat sekitar menjadi bagian dari ekosistem SR.
Transfer inovasi. Praktik baik SR wajib diadopsi oleh sekolah umum di daerah lain.
Jika prinsip-prinsip ini dijalankan, Sekolah Rakyat dapat menjadi jembatan menuju keadilan sosial, bukan monumen politik.
Kebijakan pendidikan bukanlah sekadar urusan teknokratis, tetapi cermin moral bangsa.
Sekolah Rakyat datang membawa janji besar yaitu memberi kesempatan bagi anak-anak miskin untuk hidup lebih bermartabat. Namun janji itu hanya berarti jika dijalankan dengan etika, data, dan kesetaraan.
Sekolah Rakyat adalah ujian bagi negara, apakah sungguh berkomitmen menciptakan keadilan substantif, atau sekadar mengulang retorika pemerataan. Jawabannya tidak akan lahir dari seremoni peresmian, melainkan dari kenyataan apakah anak-anak yang dulu miskin kini bisa menatap masa depan dengan kepala tegak? Jika itu terjadi, maka Sekolah Rakyat akan tercatat sebagai tonggak baru sejarah pendidikan Indonesia, bukan proyek populis, melainkan perwujudan nyata cita-cita konstitusional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa secara adil dan manusiawi. Semoga.
KARTONO
Mahasiswa Doktoral Ilmu Sosial FISIP Universitas Airlangga