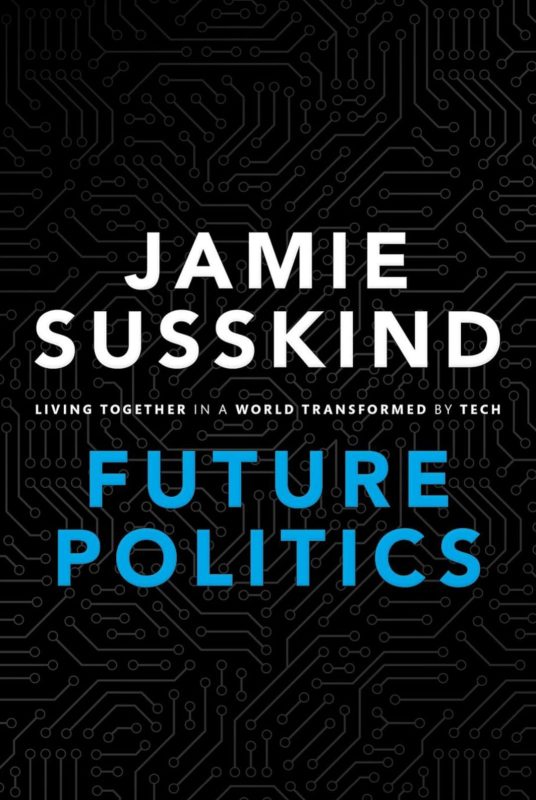
SURABAYA, CAKRAWARTA.com – “The future stalks us,” tulis Jamie Susskind di awal bukunya Future Politics: Living Together in a World Transformed by Tech. Masa depan, katanya, tidak datang perlahan; ia mengintai, menunggu di tikungan, dan sering kali menelan kita tanpa peringatan.
Kalimat pembuka itu menjadi kunci bagi seluruh isi buku, menjadi sebuah ajakan untuk berhenti bersikap pasif terhadap gelombang digitalisasi yang telah menyusup ke setiap sendi kehidupan politik. Susskind menulis bukan sekadar sebagai pengamat teknologi, tetapi sebagai pemikir politik yang gelisah, seseorang yang menyadari bahwa demokrasi, kebebasan, dan keadilan di abad ke-21 tidak akan lagi ditentukan oleh parlemen, melainkan oleh code, algoritma, dan akal imitasi.
Susskind yang merupakan lulusan hukum dari Universitas Oxford dan peneliti di Harvard’s Berkman Klein Center ini, memulai bukunya dengan satu tesis besar yaitu politik masa depan tidak lagi tentang negara versus pasar, tetapi tentang manusia versus sistem digital yang semakin berkuasa.
Kalimat kuncinya tegas bahwa, “Those who control these technologies will increasingly control the rest of us,” yang berarti mereka yang mengendalikan teknologi, mulai dari pemerintah hingga korporasi besar seperti Google dan Meta, perlahan menentukan batas kebebasan kita, mulai dari apa yang boleh diucapkan, siapa yang terlihat, bahkan bagaimana kita berpikir.
Melalui contoh-contoh konkret seperti mobil tanpa sopir yang menolak melanggar batas kecepatan, atau algoritma media sosial yang menyaring informasi sesuai profil psikologis pengguna, Susskind menegaskan: kebebasan manusia sedang diredefinisi oleh mesin.
Bagian pertama buku ini, The Digital Lifeworld, melukiskan tiga ciri utama dunia baru yaitu sistem yang semakin cerdas, teknologi yang semakin terintegrasi, dan masyarakat yang semakin terkuantisasi.
Manusia kini hidup dalam “jaring digital”, dimana tindakan, kata-kata, bahkan emosi direkam, diolah, dan diprediksi oleh sistem yang tak lagi bisa kita kendalikan.
Dalam bab-bab berikutnya, Susskind memperkenalkan konsep Future Power: Code is power. Kode yang merupakan bahasa pemrograman, algoritma, dan desain sistem, kini berfungsi seperti hukum yang mengatur perilaku sosial. Jika dulu undang-undang dibuat oleh parlemen, kini aturan ditulis oleh insinyur dan pengembang perangkat lunak.
Politik tak lagi diatur oleh pidato dan manifesto, tetapi oleh lines of code yang menentukan siapa boleh bicara, siapa disenyapkan. Dalam analogi yang kuat, Susskind menulis, “software engineers are the new philosophers, writing not with words but with code -and their ideas run the world.”
Bagian Future Liberty memperluas pembahasan ke pertanyaan klasik bahwa apa artinya bebas di dunia yang dikendalikan sistem pintar? Susskind menunjukkan paradoks yang semakin kentara yakni teknologi memberi kita kemampuan luar biasa seperti komunikasi instan, kebebasan berekspresi, akses informasi, namun di saat bersamaan, ia mempersempit ruang pilihan.
Ponsel pintar dan media sosial, misalnya, menciptakan ilusi kebebasan dimana kita merasa bebas memilih, padahal algoritma telah menentukan apa yang kita lihat dan pikirkan. “Freedom,” tulis Susskind, “is not the absence of control, but the question of who controls whom.”
Di titik inilah, buku ini terasa paling menggugah. Susskind menolak pesimisme distopia, tapi juga menghindari optimisme teknologi ala Silicon Valley. Ia memilih sikap realistis kritis bahwa kebebasan masa depan hanya bisa bertahan jika kita berani mengatur ulang relasi antara warga, negara, dan mesin.
Bagian keempat, Future Democracy, menjadi jantung moral buku ini. Susskind menulis dengan nada waspada bahwa demokrasi tak lagi bisa dipertahankan hanya lewat pemilu dan partisipasi politik konvensional. Dalam dunia di mana opini publik dibentuk oleh algoritma, kedaulatan rakyat bisa tergerus tanpa kita sadari.
Ia mengulas ide tentang data democracy dan AI democracy, sebuah bentuk pemerintahan yang mungkin di masa depan, dimana partisipasi politik bisa dilakukan langsung melalui sistem digital, dan bahkan kebijakan publik diambil dengan bantuan artificial intelligence atau akal imitasi (AI).
Namun Susskind juga mengingatkan bahwa demokrasi digital yang efisien tidak selalu demokratis.“A government that knows everything about its citizens,” tulisnya, “may not need to repress them -because it already controls what they think.”
Kutipan itu terasa relevan di tengah maraknya politik data dan pengawasan digital di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Salah satu bagian paling memikat adalah Future Justice, di mana Susskind memeriksa bagaimana algoritma membentuk keadilan sosial. Ia menyoroti kasus-kasus nyata: sistem pengenalan wajah yang bias rasial, perangkat lunak rekrutmen yang mendiskriminasi perempuan, hingga robot penilai kredit yang mengulang pola ketidakadilan lama.
Susskind menyebut fenomena ini sebagai “algorithmic injustice”, ketidakadilan yang tidak dilakukan manusia, tetapi oleh sistem yang diciptakan manusia.
Ia bertanya dengan getir yakni bagaimana menuntut keadilan pada sesuatu yang tak punya niat, tak punya nurani? Di sinilah, katanya, kita memerlukan etika baru, bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk mesin.
Bagian penutup buku, Future Politics, menawarkan refleksi tajam tentang masa depan demokrasi. Susskind membayangkan masa di mana manusia hidup dalam sistem digital yang begitu kompleks, hingga konsep politik tradisional kehilangan makna. Ketika keputusan publik diambil oleh AI yang lebih cepat, akurat, dan objektif, apakah manusia masih dibutuhkan dalam pemerintahan?
Ia menolak menyerah pada determinisme teknologi. Baginya, justru sekaranglah saatnya kita menulis ulang teori politik yakni dengan menciptakan ilmu politik baru untuk dunia yang baru, meminjam istilah Alexis de Tocqueville.
Untuk itu, Susskind mengusulkan dua prinsip utama. Pertama, adanya transparansi digital, agar kekuasaan teknologi tidak beroperasi dalam kegelapan. Kedua, adanya new separation of powers, agar tidak ada satu entitas, baik negara maupun korporasi, yang menguasai seluruh sistem pengawasan, paksaan, dan kontrol persepsi.
Future Politics bukan buku yang ringan. Gaya Susskind akademis, namun ditulis dengan semangat literer yang hidup. Ia menenun filsafat politik klasik mulai dari Hobbes, Mill, hingga Rawls, dengan realitas kontemporer tentang AI, big data, dan media sosial.
Yang membuatnya istimewa adalah kemampuan Susskind menyatukan dua dunia yaitu teknologi dan humaniora. Ia menyebut dirinya bukan sekadar lawyer atau futurist, tetapi philosophical engineer atau seorang insinyur filsafat yang mencoba membangun masa depan dengan berpikir kritis.
Buku ini menantang pembaca untuk tidak sekadar kagum pada inovasi, tapi juga curiga padanya. Susskind menulis dengan nada yang sekaligus menggugah dan mengingatkan, “technology affects us not just as consumers but as citizens. In the twenty-first century, the digital is political.”
Dalam dunia yang ditandai oleh akal imitasi dan dominasi algoritma, Future Politics adalah semacam alarm intelektual. Ia mengajak kita bertanya sebelum terlambat yaitu siapa yang akan memerintah di masa depan, manusia atau mesin?
Bagi pembaca Indonesia, buku ini relevan bukan hanya karena kebangkitan ekonomi digital dan politik media sosial, tapi juga karena kita tengah berada di persimpangan serupa yakni antara efisiensi teknologi dan martabat manusia. Di tangan Jamie Susskind, masa depan politik tidak dibayangkan sebagai kehancuran, tetapi sebagai tugas moral bersama untuk memastikan bahwa kemajuan digital tidak menghapus kemanusiaan. Semoga.
Data Buku:
Judul: Future Politics: Living Together in a World Transformed by Tech
Penulis: Jamie Susskind
Penerbit: Oxford University Press, 2018
Tebal: 512 halaman
(*)
Kontributor: Tommy
Editor: Abdel Rafi



