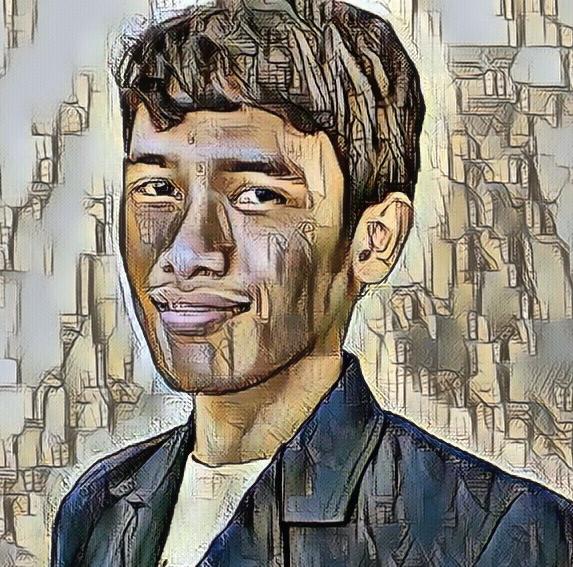
Kota Surabaya baru saja melakukan grand launching Kota Lama Surabaya, Rabu (3/7/2024). Bagian yang terletak di kawasan kecamatan Krembangan dan Pabean Cantian ini, dikonsep sedemikian rupa sehingga memadukan bangunan-bangunan arsitektur kolonial dengan penataan pedestrian yang memungkinkan masyarakat dapat berjalan sambil bernostalgia seakan mengalami de javu, kembali pada masa lampau. Cat-cat dimainkan, jalan-jalan dirapikan agar terlihat rapi dan tertata, kegiatan pun dibuat untuk membubuhkan kesan menarik dari wisatawan, begitu pula branding di media sosial yang tidak henti-hentinya masuk di timeline media sosial milik siapa saja tidak terkecuali warga Kota Surabaya.
Namun, dari sekian banyak gegap gempita dimana Kota Lama Surabaya sendiri, penulis sebagai warga menemukan beberapa catatan kritis terkait dengan wacana pengembangan kawasan ini. Belajar dari ketidaktuntasan Pemkot Surabaya dalam menata Jalan Tunjungan, yang hanya menjadi public sphere daripada public space dalam rangka citra dan jati diri sebuah kota ketika wacana pembangunan menafikan representasi Surabaya kota yang memiliki banyak kreativitas daripada sebatas bisnis berjualan makanan dan minuman semata. Tunjungan tak ayalnya sebatas pusat keramaian saja daripada menjadi ikon sebuah kota yang manusiawi dan inklusif untuk semua.
Tiga Kritik Utama
Setidaknya, terdapat tiga kritik utama terhadap penataan konsep Kota Lama Surabaya dalam pandangan penulis. Pertama, Kota Lama Surabaya tidak didesain dengan rapi dari segi arah dan tujuan pengembangannya. Kita bisa membandingkan dengan penataan “Kota Lama” di berbagai tempat, seperti Jakarta yang paling mudah dengan menjadikan kawasan Museum Fatahilah sebagai episentrum karena melekat dan terbersit bahwa Kota Lama Jakarta merupakan pusat dari ibu kota Hindia Belanda, Batavia. Wajar jika Batavia merupakan representasi inti dari akar serabut kekuasaan pemerintahan kolonial, sehingga Kota Lamanya masih dipertahankan dan menjadi ikon tersendiri khususnya di wilayah Kota Jakarta Barat.
Adapun Surabaya, dengan berbagai liku-liku sejarah politik dan budayanya, merupakan kota penting yang tidak hanya dalam konteks masa kolonial. Ia merupakan Kota Pahlawan, yang mana simbolnya terletak di Tugu Pahlawan, eks Raad van Justitie yang telah dirobohkan. Selebihnya, kronik masa lalu Surabaya adalah tentang perjuangan melawan kekuasaan mana pun yang mencoba mendobrak independensi warganya. Pada masa Hindia Belanda, setidaknya kesewenang-wenangan itu tidak datang hanya dari pemerintahan kolonial saja namun juga dari Mataram di bawah Sultan Agung yang mencoba menguasai wilayah Kadipaten Surabaya meskipun kemudian tunduk melalui strategi pengotoran Kali Mas dan perkawinan politik.
Artinya, narasi tentang Kota Surabaya yang menggambarkan akan besarnya perlawanan terhadap penjajah kabur begitu saja setelah melihat detail-detail dari nama jalan yang dinamai menggunakan Bahasa Belanda. Lihat Jembatan Merah yang dulunya dinyanyikan oleh maestro Gesang, atas nama branding dikembalikan menjadi nama Belanda yakni Roode Brug. Aspek kearifan lokal sama sekali tidak terbentuk bahwa kita adalah pihak yang pernah setidaknya ratusan tahun melawan kekuasaan Belanda yang semena-mena.
Kedua, menyedihkannya lagi narasi yang dibuat pada penataan kawasan Kya-kya Kembang Jepun dan sekitarnya akan mulai memasukkan lagi separasi wilayah berdasarkan pembagian peruntukan lahan bagi masyarakat-masyarakat yang berasal dari keturunan asing seperti Kampung Cina, Kampung Melayu, dan Kampung Arab sesuai dengan peta wilayah Kota Surabaya yang disusun oleh pemerintahan kolonial. Hal ini tentu akan kembali mengaburkan narasi besar tentang Surabaya yang terkenal menjadi melting pot peleburan dari berbagai elemen kebudayaan.
Selain itu, penataan kawasan ini tidak disertai dengan integrasi antara wacana wisata religi yang dikembangkan di sekitarnya. Kawasan religi Sunan Ampel dan Tunjungan sebagai wisata nostalgia (juga) hadir dengan polesan gemerlap lampu kota dan berdirinya kafe-kafe, atau kawasan-kawasan lain yang letaknya sangat berdekatan. Itu pun tidak dimasukkan dalam satu paket kawasan besar wisata yang terintegrasi sehingga kesan bahwa proyek pembangunan kawasan ini sebagai proyek mercusuar juga mengemuka.
Ketiga, kekhawatiran penulis semakin menjadi ketika pengembangan Kota Lama ini hanya muncul sesaat hanya untuk menciptakan leverage politik praktis saja bagi Walikota petahana Eri Cahyadi. Mengingat di bagian sebelumnya, penataan dari kawasan Tunjungan tidak partisipatif. Pemkot hanya terkesan membuat proyek-proyek mercusuar saja, dengan dipoles permainan media sosial dibantu oleh para pemengaruh (influencer) yang memiliki banyak pengikut (follower) untuk meningkatkan publisitas dari Kota yang sebenarnya memiliki program-program dengan perencanaan dan juga delivery message yang tidak tepat sasaran. Hal ini juga berlaku dengan program-program Pemkot lain yang menggunakan jasa para influencer untuk melakukan endorsement.
Proyek fisik hanya terlihat digelontorkan pada masa akhir jabatan, yang menimbulkan keresahan sebagian masyarakat di media sosial bahwasanya pembangunan dengan pendekatan shock teraphy mengingatkan pada Bandung Bondowoso, dan bukan gradual ini justru mengganggu keseharian masyarakat yang bekerja dan menjadi pengguna jalan. Terbukti dalam berbagai pengerjaan proyek Kota Lama, tampak halangan berupa penyempitan jalan yang terjadi karena pembangunan instalasi gorong-gorong di berbagai titik.
Apa yang Harus Dilakukan?
Mengantisipasi hal semacam ini tidak terjadi kembali, Pemkot Surabaya setidaknya harus melibatkan lebih banyak lagi pihak untuk berdiskusi di dalam Musrenbang Kota Surabaya. Selain kepada memadu-padankan pendapat-pendapat dari para ahli yang tidak hanya terlihat dukungan atau endorsement-nya terhadap pembangunan Kota, namun secara aktif memberi wacana kritis dan alternatif sebagai pembanding agar pembangunan dapat mempertimbangkan aspek-aspek yang nyaris tidak tersentuh. Artinya, pembangunan kota termasuk pembentukan ikon Kota Surabaya dapat dipertimbangkan dengan masak.
Terlebih, pembangunan Kota Lama ini seolah memudarkan spirit Kota Surabaya sebagai kota Pahlawan dengan kembali menggulirkan istilah dan tampilan era kolonial, namun tidak dengan baik mengemasnya dengan berbagai aktivitas atau kegiatan penunjang yang menonjolkan narasi sejarah berkaitan dengan peristiwa penting yang justru esensial di kawasan itu: tertembaknya AWS Mallaby, dan tentu slogan yang justru ditinggalkan: “Once and Forever Indonesian Republic.”
Wacana nasionalisme dan heroisme, aspek penghargaanlah sebagai esensi yang hilang dari kawasan itu alih-alih hanya sebatas bangunan yang secara fisik kuno dan sebatas dipoles dengan pernak-pernik.
PROBO DARONO YAKTI
Dosen FISIP Universitas Airlangga dan Pemerhati Sejarah Kota Surabaya



