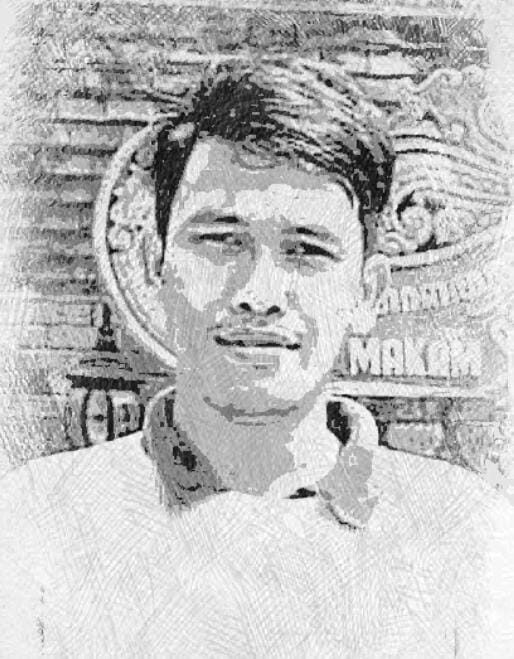
Reformasi 1998 adalah momen penting yang mengakhiri dominasi militer dalam pemerintahan Indonesia. Salah satu pencapaian utamanya adalah menegaskan supremasi sipil dan membatasi peran TNI hanya dalam ranah pertahanan. Namun, dengan adanya revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang sedang dibahas, kita dihadapkan pada ancaman nyata akan kembalinya militer sebagai aktor utama dalam politik dan birokrasi. Yang lebih mencemaskan, upaya ini diiringi dengan sikap anti kritik yang semakin mengemuka dari kalangan petinggi militer.
Pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang menyebut para pengeritik revisi UU TNI sebagai “kampungan” adalah cerminan dari arogansi militer yang menolak diawasi. Sikap ini bukan hanya menunjukkan bahwa TNI masih melihat dirinya sebagai entitas yang tak tersentuh kritik, tetapi juga mengingatkan pada masa Orde Baru, dimana militer menjadi kekuatan yang tidak bisa digugat. Jika kritik dari masyarakat sipil saja dianggap sebagai gangguan, bagaimana mungkin supremasi sipil dapat tetap tegak?
Kembalinya Militer Sebagai Kelas Elite?
Revisi UU TNI tidak hanya membuka jalan bagi perwira aktif untuk menduduki jabatan sipil, tetapi juga memperkuat posisi militer dalam struktur negara. Beberapa kasus terbaru mengindikasikan bahwa militer semakin leluasa memasuki ranah sipil dengan cara yang tidak transparan.
Salah satu contoh paling mencolok adalah penunjukan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog. Jabatan ini seharusnya diisi oleh seorang profesional dengan latar belakang ekonomi dan manajemen logistik, bukan perwira aktif militer. Selain itu, kasus kenaikan pangkat “instan” Letkol Inf Teddy Indra Wijaya menjadi Sekretaris Kabinet juga menimbulkan pertanyaan besar. Teddy dipromosikan dari Mayor menjadi Letnan Kolonel dalam waktu singkat, tanpa melalui mekanisme reguler yang berlaku di Mabes TNI, melainkan hanya melalui surat perintah.
Dua kasus ini bukanlah kebetulan, melainkan indikasi dari tren yang lebih besar: jalur cepat bagi perwira militer masuk ke ranah sipil tanpa prosedur semestinya. Jika terus terjadi, perwira aktif TNI akan memiliki privilese lebih dibanding birokrat sipil, menciptakan ketimpangan dalam meritokrasi. Bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan, lebih banyak perwira aktif ditempatkan di kementerian, lembaga negara, bahkan BUMN dengan dalih efisiensi dan kepemimpinan tegas. Namun, ini justru berisiko menjadikan militer kembali sebagai kelas elite yang mengatur negara, seperti era Orde Baru.
Anti Kritik dan Pembungkaman: Tanda-Tanda Bahaya
Selain kembalinya peran militer dalam birokrasi sipil, meningkatnya respons represif terhadap kritik menjadi ancaman nyata bagi demokrasi. Pernyataan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang menyebut kritik terhadap revisi UU TNI sebagai “kampungan” menunjukkan arogansi militer yang enggan diawasi. Sikap seperti ini mengingatkan pada masa Orde Baru, ketika kritik terhadap militer dianggap sebagai ancaman dan bukan bagian dari demokrasi. Jika mentalitas ini terus dibiarkan, supremasi sipil yang menjadi fondasi Reformasi 1998 akan semakin terkikis.
Belum lagi mengenai kasus “intimidasi” terhadap Kantor KontraS setelah organisasi tersebut mengeritik revisi UU TNI semakin memperjelas pola pembungkaman yang sistematis. Ini mencerminkan praktik era Orde Baru, ketika kritik terhadap militer sering kali dibalas dengan represi dan ancaman tersembunyi. Jika hal seperti ini dibiarkan, masyarakat sipil akan semakin takut untuk bersuara, sementara militer semakin bebas mengonsolidasikan kekuasaannya dalam pemerintahan. Demokrasi yang sehat tidak akan bertahan jika kebebasan berpendapat justru dianggap sebagai ancaman.
Di media sosial, buzzer atau para pendengung yang didanai oleh kepentingan tertentu menggiring opini bahwa revisi UU TNI adalah solusi bagi pemerintahan yang lebih efektif dan bebas korupsi. Narasi ini menyesatkan karena menyederhanakan solusi atas birokrasi yang buruk seolah-olah hanya bisa diperbaiki dengan militerisasi. Mereka yang menolak gagasan ini sering kali dicap sebagai anti pemerintah atau dianggap tidak memahami sejarah. Padahal, justru mereka yang meromantisasi peran militer dalam pemerintahan yang gagal belajar dari “sejarah kelam” Dwi Fungsi ABRI.
Generasi muda, terutama Generasi Z, menjadi sasaran utama propaganda ini karena mereka tidak mengalami langsung represi di era Orde Baru. Mereka cenderung melihat stabilitas dan ketegasan sebagai keunggulan militer tanpa menyadari bahaya supremasi militer dalam politik. Jika masyarakat tidak segera melawan narasi ini, semakin banyak orang yang menerima gagasan bahwa supremasi sipil tidak lagi relevan. Jika dibiarkan, bukan hanya kritik yang akan dibungkam, tetapi juga hak-hak demokratis yang telah diperjuangkan sejak Reformasi 1998.
Mengapa Kita Harus Waspada?
Banyak yang menganggap bahwa masuknya perwira aktif ke dalam birokrasi bukanlah masalah besar, terutama jika diklaim dapat meningkatkan efisiensi dan disiplin pemerintahan. Namun, perlu diingat bahwa birokrasi sipil dan militer memiliki prinsip kerja yang berbeda. Militer bekerja dalam sistem hierarki komando, dimana perintah harus dijalankan tanpa banyak pertimbangan. Sementara itu, birokrasi sipil menuntut transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan. Jika militer semakin banyak mengisi posisi sipil, maka pengelolaan negara akan semakin kaku dan tertutup, mengikis sistem demokratis yang telah diperjuangkan selama dua dekade terakhir.
Lebih dari itu, revisi UU TNI ini membuka ruang bagi kembalinya militer sebagai aktor dominan dalam pemerintahan. Dengan menempatkan perwira aktif di berbagai lembaga sipil dan BUMN, militer perlahan-lahan mendapatkan kembali akses terhadap kekuasaan yang seharusnya berada di tangan sipil. Bahaya laten ini bukan hanya tentang dominasi struktural, tetapi juga tentang perubahan budaya politik yang berorientasi pada pendekatan koersif dan otoriter. Demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi musyawarah dan keseimbangan kekuasaan bisa tergantikan oleh gaya kepemimpinan militer yang lebih menekankan kepatuhan dan kontrol ketat.
Jika masyarakat tetap diam, maka revisi UU TNI akan berjalan tanpa hambatan, membawa kembali ke era ketika militer adalah penentu utama jalannya negara. Kebijakan ini akan mengikis peran sipil dan menjadikan TNI kembali sebagai kekuatan politik yang tak tersentuh kritik. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin di masa depan kita akan menghadapi kondisi di mana supremasi sipil benar-benar runtuh, dan Reformasi 1998 hanya menjadi sekadar catatan sejarah yang terlupakan. Sekaranglah waktunya bagi masyarakat sipil untuk bersuara dan memastikan bahwa demokrasi tetap menjadi pilar utama dalam tata kelola negara.
PROBO DARONO YAKTI
Direktur Center for National Defense and Security Studies (CNDSS)
Dosen FISIP Universitas Airlangga



