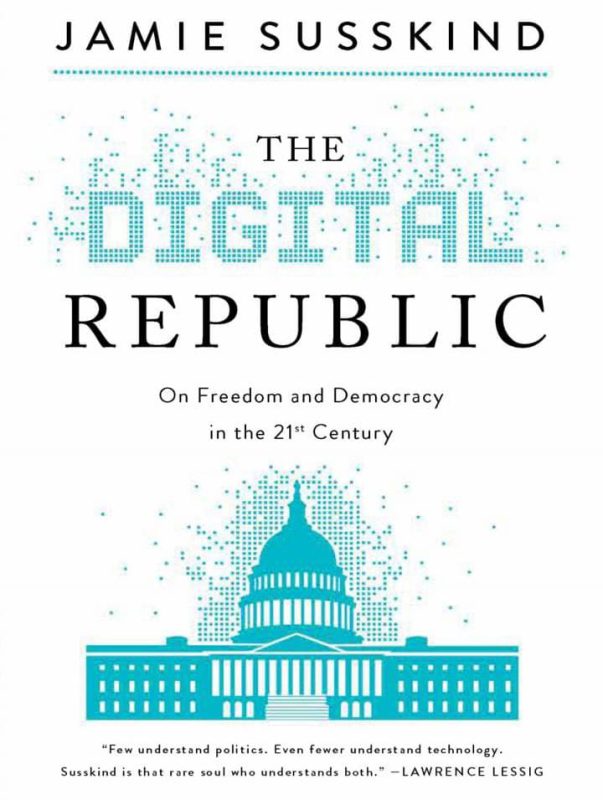
SURABAYA, CAKRAWARTA.com – Apakah kebebasan dan demokrasi masih bisa bertahan di abad digital? Pertanyaan ini menjadi poros besar dalam buku terbaru Jamie Susskind, The Digital Republic: On Freedom and Democracy in the 21st Century (Pegasus Books, 2022). Dalam karya ini, sang pengacara muda asal Inggris yang juga penulis Future Politics (2018) itu mengajukan sebuah tesis tajam yakni kekuatan politik terbesar abad ke-21 tidak lagi berada di parlemen atau istana, tetapi di ruang server dan barisan kode yang ditulis oleh para insinyur perangkat lunak.
Susskind mengajak pembaca menyadari bahwa “code is law” dimana kode komputer telah menjadi hukum baru yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan di dunia digital. Dari algoritma media sosial hingga sistem artificial intelligence atau akal imitasi (AI) yang menentukan pinjaman, pekerjaan, bahkan pasangan, teknologi kini mengatur perilaku manusia dengan cara yang nyaris tak terlihat, tanpa akuntabilitas politik yang jelas.
Bab pembuka buku ini menyajikan sebuah sindiran ironis dimana kalau dulu, teknologi digital dipuja sebagai pembebas manusia dan pelindung demokrasi. Namun kini, teknologi digital menjadi sumber kekhawatiran baru, yang menciptakan ketimpangan kekuasaan yang tak pernah dibayangkan. Susskind menulis dengan gaya reflektif, “Those who write code increasingly write the rules by which the rest of us live.” Mereka yang menulis kode, pada hakikatnya, menulis undang-undang kehidupan modern.
Dengan menelusuri dinamika Silicon Valley, ia menunjukkan bahwa para raksasa teknologi seperti Google, Facebook, Amazon, Apple, telah tumbuh melampaui kendali hukum dan politik tradisional. Mereka bukan sekadar perusahaan dagang, melainkan kekuatan sosial yang membentuk cara kita berpikir, berinteraksi, dan memahami dunia.
Ketika Facebook menurunkan artikel kontroversial tentang Hunter Biden pada 2020, keputusan itu bukan diambil oleh lembaga demokratis, melainkan oleh tim moderasi korporat. Pertanyaannya, kata Susskind, bukan apakah mereka bertindak benar, melainkan, “mengapa mereka punya hak untuk memutuskan hal itu?”
Susskind memperkenalkan istilah unaccountable power yaitu kekuasaan yang besar tanpa pertanggungjawaban publik. Ia menolak pandangan bahwa penyalahgunaan teknologi Adalah akibat dari beberapa “orang jahat” di perusahaan besar. Masalahnya lebih dalam bahwa kita gagal mengatur teknologi secara demokratis.
Ia lalu memperkenalkan konsep yang disebut sebagai digital republicanism, yakni ide bahwa kebebasan sejati hanya bisa ada bila tidak ada satu kekuatan pun baik itu negara maupun korporasi, yang dapat mendominasi kehidupan warga tanpa mekanisme kontrol publik. Ini mengingatkan kita pada semangat republik klasik Romawi yang menolak dominium, kekuasaan tanpa batas dari individu atau kelompok atas yang lain.
Dalam pandangan Susskind, kebebasan di era digital bukan hanya soal melindungi privasi atau memilih layanan daring, tetapi hak untuk tidak hidup di bawah kekuasaan tersembunyi algoritma. Ia menulis dengan tegas bahwa “freedom does not mean having a just master. It means having no master at all.”
Buku Susskind ini juga merupakan kritik filosofis terhadap ideologi yang disebutnya market individualism yaitu sebuah keyakinan bahwa pasar bebas dan inisiatif individu cukup untuk menjamin kemajuan dan kebebasan. Dalam praktiknya, kata Susskind, pandangan ini justru membuat publik menyerahkan kendali atas kehidupan digital kepada segelintir korporasi global. Demi inovasi, kita rela menukar hak politik dengan kemudahan dan kenyamanan.
Lalu Susskind menawarkan jalan alternatif yaitu digital republicanism, yang menekankan empat prinsip utama mulai dari menjaga institusi demokrasi dari dominasi teknologi; mengurangi kekuasaan tak terkontrol dari perusahaan digital; memastikan teknologi mencerminkan nilai-nilai moral masyarakat; dan membatasi campur tangan negara agar tak berubah menjadi pengawas digital total.
Susskind menyarankan pembentukan lembaga-lembaga baru, standar etik bagi insinyur teknologi, dan kerangka hukum yang setara dengan profesi dokter atau pengacara. Para arsitek digital, katanya, harus tunduk pada prinsip moral publik, bukan hanya logika pasar.
Kekuatan buku ini bukan semata pada argumentasi hukum dan politiknya, melainkan pada kemampuannya membingkai ulang persoalan teknologi sebagai masalah etika publik dan kemanusiaan. Susskind tidak terjebak dalam moral panik ala anti teknologi. Ia bukan Luddit baru yang menolak kemajuan, melainkan seorang republikan modern yang bertanya, “apakah kemajuan digital masih setia pada cita-cita kebebasan?”
Dengan narasi yang tajam dan bergaya elegan, Susskind menulis layaknya filsuf politik kontemporer. Ia mengutip Cicero, Madison, dan Arendt untuk menegaskan bahwa demokrasi selalu berhadapan dengan godaan kekuasaan yang tak terkontrol, dan di abad ke-21, kekuasaan itu bernama algorithmic governance.
Buku ini juga memukau karena berhasil menghubungkan sejarah gagasan politik klasik dengan realitas digital. Dari republik Romawi hingga revolusi Amerika, Susskind menunjukkan bahwa perjuangan melawan dominasi adalah tema abadi yang kini berwujud baru yakni perlawanan terhadap algoritma yang menentukan hidup manusia.
Meski bersifat analitis, The Digital Republic tidak kehilangan sisi humanistiknya. Susskind mengakui daya tarik teknologi bagi miliaran orang mulai dari kemudahan, efisiensi, bahkan kebahagiaan. Namun ia menolak pandangan bahwa kemajuan digital harus dibayar dengan kehilangan kedaulatan manusia.
“Tidak ada rezim lama yang sepenuhnya menindas,” tulisnya mengutip Michael Walzer. “Setiap sistem lama selalu memiliki daya tarik.” Karena itu, membangun republik digital bukan berarti mematikan inovasi, tetapi menjadikannya tunduk pada prinsip kemanusiaan dan akuntabilitas.
Buku ini, menjadi semacam manifesto etika politik untuk abad digital. Ia mengingatkan kita bahwa demokrasi tidak akan mati secara tiba-tiba, melainkan terkikis perlahan oleh kemudahan yang kita nikmati tanpa sadar. Dalam dunia yang diatur oleh kode, kebebasan membutuhkan bentuk baru yakni kewargaan digital yang kritis, berdaulat, dan sadar akan kekuasaan di balik layar.
Dalam konteks Indonesia, gagasan Susskind terasa relevan. Di tengah euforia transformasi digital, kita kerap lupa bahwa teknologi bukan netral. Dari algoritma berita yang membentuk opini publik hingga platform yang mempengaruhi perilaku politik, ruang digital menjadi arena kekuasaan baru yang belum sepenuhnya diawasi.
Melalui The Digital Republic, Susskind mengajak pembaca berpikir ulang apakah kita sekadar pengguna, atau warga republik digital yang punya hak menentukan arah masa depan teknologi? Pertanyaan ini seharusnya menggugah para pembuat kebijakan, akademisi, dan jurnalis di negeri ini untuk menuntut transparansi, etika, dan akuntabilitas dalam setiap inovasi digital yang menyentuh publik.
Buku ini bukan bacaan ringan. Ia menuntut perhatian, tetapi menghadiahi pembacanya dengan wawasan luas tentang politik kekuasaan baru di era data dan algoritma. Jamie Susskind tampil bukan sekadar sebagai pengamat teknologi, melainkan filsuf republik masa depan. Ia percaya bahwa kebebasan manusia masih mungkin dipertahankan, asalkan kita berani menegakkan prinsip lama dalam dunia baru yakni tak seorang pun, termasuk algoritma, boleh berkuasa tanpa pertanggungjawaban. Semoga.
Data Buku:
- Judul: The Digital Republic: On Freedom and Democracy in The 21th Century
- Penulis: Jamie Susskind
- Penerbit: Pegasus Books
- Tahun: 2022
- Tebal: 379 halaman
(*)
Kontributor: Tommy
Editor: Abdel Rafi




republik digital dan kebebasan manusia adalah pembahasan yang bermanfaat. Dalam dinamika dunia digital yang terus berkembang pesat, peluang untuk berinovasi kini hadir di berbagai bidang tanpa batas. Virtual Reality Indonesia menghadirkan pengalaman interaktif yang bukan hanya menawan secara visual, tetapi juga mampu membangun kedekatan emosional, menciptakan hubungan yang kuat antara pengguna dan konten di setiap momen digital.