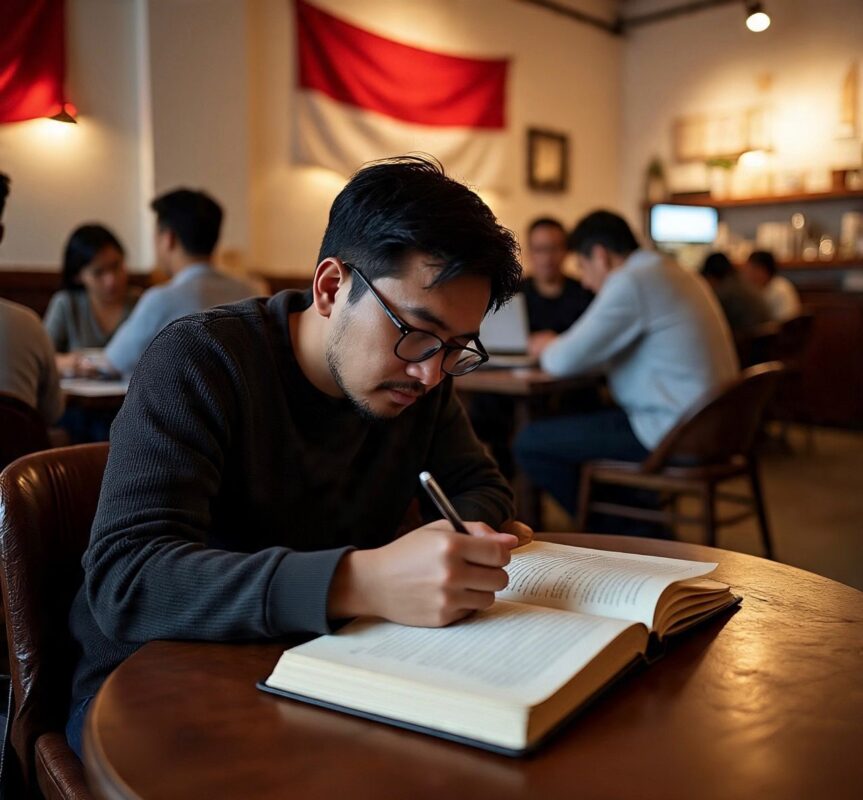
“Perkembangan sastra Indonesia erat kaitannya dengan munculnya kesadaran nasional.” — Keith Foulcher (79), Indonesia and National Literatures: Some Preliminary Considerations (1982).
Lebih dari satu abad telah berlalu sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 menggemakan semangat kebangsaan yang menyatukan bahasa, tanah air, dan bangsa Indonesia. Namun, gema itu tidak berhenti sebagai dokumen sejarah.
Tiap bulan Oktober, sebagai bulan bahasa, ia menjelma menjadi medan tafsir, ruang kontestasi, dan sumber pencarian makna baru tentang nasionalisme di tengah dunia yang terus berubah.
Dalam lanskap sastra kontemporer, puisi esai hadir bukan sekadar sebagai bentuk estetika, melainkan sebagai medium reflektif yang menginterogasi ulang ide kebangsaan.
Terbitan puisi-puisi esai oleh Satupena, misalnya, menunjukkan bahwa nasionalisme hari ini bukan lagi monolitik, melainkan cair, kompleks, dan sering kali penuh paradoks.
Mengacu pada rintisan awal puisi esai Atas Nama Cinta (2012) karya Denny JA, ide nasionalisme muncul secara implisit melalui narasi tentang perjuangan melawan diskriminasi dan pencarian keadilan dalam bingkai kebangsaan.
Salah satu frase yang mengandung semangat nasionalisme adalah, “Negara ini milik semua. Tak satu pun boleh ditolak karena cinta yang berbeda.”
Kutipan ini menegaskan bahwa nasionalisme Indonesia harus bersifat inklusif, menjamin hak setiap warga tanpa diskriminasi, dan menempatkan cinta sebagai nilai universal yang melampaui batas identitas.
Dalam konteks puisi esai, nasionalisme bukan hanya soal tanah air, tetapi juga soal keberanian untuk memperjuangkan kesetaraan dan kemanusiaan dalam ruang kebangsaan
Keith Foulcher, Indonesianist asal Australia, khususnya dalam kajian sastra Indonesia modern dan wacana kebangsaan, dalam Indonesia and National Literatures: Some Preliminary Considerations, mengingatkan bahwa sastra Indonesia modern lahir dari ketegangan antara lokalitas dan nasionalitas.
Sastra tidak hanya mencerminkan bangsa, tetapi juga membentuknya.
Dalam puisi esai, ketegangan itu menjadi ruang produktif di mana penyair tidak hanya merayakan Indonesia, tetapi juga mengkritiknya.
Nasionalisme dalam puisi esai bukan slogan, melainkan pertanyaan: tentang siapa yang berhak bicara atas nama bangsa, tentang siapa yang terpinggirkan dalam narasi besar kebangsaan, dan tentang bagaimana bahasa Indonesia menjadi medan politik dan budaya.
Prof. Dr. Faruk, pengajar sastra di FIB UGM, dalam Nasionalisme Puisi: Sastra, Politik dan Kajian Budaya (2018) menekankan bahwa puisi bukan hanya ekspresi individual, tetapi juga representasi ideologis.
Puisi esai, dengan bentuknya yang naratif dan reflektif, menjadi ruang di mana sejarah, politik, dan identitas berkelindan.
Di dalamnya, nasionalisme tidak hadir sebagai dogma, tetapi sebagai proses negosiasi antara kenangan dan harapan, antara luka dan cita.
Puisi esai menjadi arsip emosional bangsa, di mana suara-suara yang terpinggirkan -perempuan, minoritas, daerah, dan kelas bawah- mendapat ruang untuk berbicara.
Ben Anderson dalam Imagined Communities menyatakan bahwa bangsa adalah komunitas yang dibayangkan, dibentuk oleh narasi dan media.
Puisi esai, dalam konteks ini, menjadi media alternatif yang membayangkan ulang Indonesia.
Ia tidak hanya mengulang narasi resmi, tetapi juga membongkarnya, menantangnya, dan kadang menolaknya.
Dalam puisi esai, Indonesia bukan hanya peta, tetapi juga rasa. Bukan hanya sejarah, tetapi juga trauma. Bukan hanya cita-cita, tetapi juga kritik.
Dalam buku Sosiologi Sastra (2020) Prof. Dr. Sapardi Djoko Damono (1940-2020) menulis, “Sastra bisa mengandung gagasan yang mungkin dimanfaatkan untuk menumbuhkan sikap sosial dalam suatu masyarakat – atau bahkan untuk mencetuskan peristiwa sosial tertentu.”
Pernyataan ini menunjukkan bahwa karya sastra tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi estetika, tetapi juga sebagai alat pembentuk kesadaran kolektif, termasuk nasionalisme.
Sastra menjadi medium di mana nilai-nilai kebangsaan, identitas, dan solidaritas sosial dapat dirumuskan, dipertanyakan, dan disebarkan.
Sapardi juga menekankan bahwa latar sosial pengarang dan struktur masyarakat tempat karya itu lahir sangat memengaruhi isi dan bentuk sastra.
Dalam konteks nasionalisme, ini berarti bahwa sastra Indonesia modern adalah hasil dari pergulatan sosial-politik yang melahirkan semangat kebangsaan, seperti yang tercermin dalam Sumpah Pemuda dan gerakan sastra nasional.
Di tengah dunia yang disebut Kenichi Ohmae (82) sebagai The Borderless World (1999), nasionalisme Indonesia menghadapi tantangan baru.
Globalisasi, digitalisasi, dan migrasi budaya membuat batas-batas kebangsaan semakin kabur. Ia katakan, “Batas negara tidak sepenting dulu. Persaingan yang sesungguhnya adalah antara ekonomi regional dan perusahaan global.“
Namun, puisi esai justru menemukan relevansinya di sini. Ia menjadi ruang untuk merumuskan ulang nasionalisme yang tidak eksklusif, tetapi inklusif.
Nasionalisme yang tidak menutup diri, tetapi membuka dialog. Nasionalisme yang tidak hanya mengingat masa lalu, tetapi juga merancang masa depan.
Sumpah Pemuda, puisi esai menjadi saksi bahwa nasionalisme Indonesia masih hidup, meski tidak selalu sehat, tidak selalu utuh, dan tidak selalu disepakati. Ia hidup dalam pertanyaan, dalam kritik, dan dalam harapan.
Dan selama puisi masih ditulis, dibaca, dan diperdebatkan, maka Indonesia sebagai ide akan terus diperjuangkan.
#coverlagu: Lagu „Indonesia Pusaka“(Cipt. Ismail Marzuki), komponis legendaris Indonesia yang dikenal dengan karya-karya bernuansa perjuangan dan cinta tanah air.
Versi Shanna Shannon pertama kali mengunggah cover lagu “Indonesia Pusaka” pada tahun 2015, saat usianya masih 9 tahun.
Versi ini menjadi viral dan ditonton jutaan kali di YouTube, memperkuat citranya sebagai Duta Lagu Kebangsaan Indonesia.
ReO FIKSIAWAN
Penulis dan Sastrawan Senior



