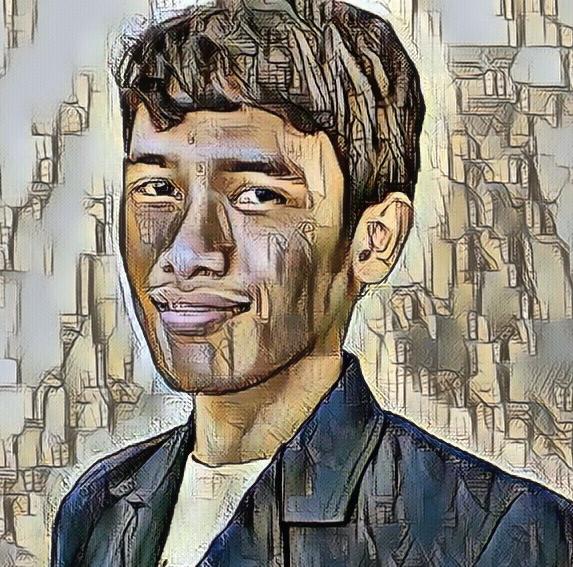
Keputusan yang berubah-ubah dan plin-plan dalam pemerintahan sering kali mencerminkan ketidakjelasan dalam kepemimpinan. Baru-baru ini, Hasan Nasbi mundur dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO). Keputusan itu dianggap gentleman, tetapi beberapa saat kemudian, Presiden Prabowo Subianto justru meminta Hasan kembali. Kejadian ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang konsistensi dan ketegasan dalam pengambilan keputusan serta peran komunikasi yang ada di dalamnya.
Sebelum mundur, ada beberapa blunder yang mencolok dari Hasan Nasbi yang patut dicatat. Salah satunya adalah insiden mengenai laporan yang diterimanya tentang seorang “Kepala Babi” yang dikirimkan ke kantor Media Tempo. Ketika itu, respons Hasan yang sangat tidak profesional dan culas adalah hanya mengatakan, “Dimasak saja.” Respons ini, yang seharusnya mencerminkan kecermatan dan ketelitian, justru menunjukkan ketidakmampuan untuk menangani isu penting dengan serius. Tak hanya itu, sikap seperti ini menggugurkan fungsi komunikasi kepresidenan yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menyampaikan kebijakan secara jelas dan tepat.
Blunder serupa terjadi dalam beberapa kesempatan sebelumnya. Salah satunya adalah ketidaktepatan dalam memberikan klarifikasi terkait isu-isu penting yang berkembang di media, yang justru memperburuk citra dan kredibilitas kantor komunikasi tersebut. Respons yang terlambat atau tidak memadai terhadap kritik dan pemberitaan yang berkembang membuat kantor komunikasi presidensial kehilangan arah dan fungsi utama sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat.
Menyikapi ketidakmampuan dengan bijak
Mengundurkan diri seharusnya dipandang sebagai tindakan mulia dalam budaya kita, bukan sebagai kegagalan. Dalam budaya ketimuran, jika seseorang merasa tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, mengundurkan diri adalah bentuk tanggung jawab moral. Ini tercermin dalam tradisi Jepang, di mana pejabat yang terbukti melakukan kesalahan besar atau tidak mampu melaksanakan tugas memilih untuk mundur sebagai bentuk pengakuan. Sebagai contoh, pada 2012, Menteri Pertahanan Jepang Yasuo Ichikawa mengundurkan diri setelah terungkap penyalahgunaan dana publik. Keputusan Ichikawa mencerminkan integritas tinggi, bahwa lebih baik mundur daripada mempertahankan posisi yang seharusnya tidak dijabat.
Namun, pengunduran diri Hasan Nasbi yang kemudian dibatalkan, justru menimbulkan kebingungan. Keputusan yang plin-plan ini menunjukkan betapa sulitnya mendapatkan kepemimpinan yang tegas dan konsisten. Ketika seorang pejabat mengundurkan diri karena merasa tidak mampu, lalu keputusan tersebut dibatalkan, kita bertanya: apa yang sebenarnya terjadi? Apakah keputusan itu didasarkan pada pertimbangan yang matang, atau hanya sekadar respons terhadap tekanan eksternal?
Di dunia politik, ketegasan sangat penting. Keputusan yang diambil harus solid dan tidak mudah berubah hanya karena berbagai alasan. Pemimpin yang baik harus berani untuk membuat keputusan dan mempertahankan keputusan tersebut, bukan sekadar mencari jalan keluar yang mudah.
Mengembalikan Pola Komunikasi Kepresidenan
Kantor Komunikasi Kepresidenan, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menyampaikan kebijakan dan arah pembangunan kepada publik, kini sering kali terkesan hanya menjadi alat untuk membenarkan kebijakan yang ada. Fungsi utama kantor ini, yang seharusnya menjelaskan visi dan misi pemerintahan kepada masyarakat, malah digantikan oleh juru bicara yang hanya bertugas menyampaikan pesan tanpa makna yang mendalam.
Pada masa pemerintahan Soeharto, Moerdiono dikenal sebagai sosok juru bicara yang memiliki kemampuan luar biasa dalam menyampaikan kebijakan. Ia dikenal dengan sikap kalem dan tenangnya, mampu memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami tanpa terjebak dalam pemberitaan yang sensasional. Hal ini sangat berbeda misalnya dengan Fadjroel Rahman di era Pemerintahan Joko Widodo, yang meskipun memiliki semangat tinggi, sering terjebak dalam penyampaian yang berlebihan, sehingga terkesan kurang matang dan hiperbolis. Keputusan untuk memindah Fadjroel menjadi Duta Besar menunjukkan pentingnya memilih juru bicara yang tidak terjebak dalam permainan politik atau media sosial.
Menghadirkan Sosok Juru Bicara yang Tenang dan Bersahaja
Memang, Prabowo telah menunjuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk menjadi juru bicara kepresidenan. Namun lebih penting bagi Presiden Prabowo untuk memilih juru bicara yang mampu menjaga kewibawaan dan netralitas, bukan hanya berdasarkan faktor usia atau popularitas. Sebagai contoh, Moerdiono bukan hanya mampu menyampaikan informasi, tetapi juga menjaga ketenangan dalam situasi yang penuh tekanan. Juru bicara yang ideal harus bisa mengelola komunikasi dengan bijaksana, tidak terpengaruh oleh sentimen media atau opini yang berkembang. Ia harus mampu menjelaskan kebijakan dengan tenang dan tetap menjaga sikap netral tanpa terbawa emosi.
Di dunia yang semakin dipenuhi dengan informasi cepat dan media sosial, peran juru bicara tidak hanya tentang berbicara cepat atau banyak, tetapi lebih kepada kemampuan untuk mendengarkan dan memahami situasi. Ini membutuhkan orang yang memiliki pengalaman dan kedewasaan dalam mengelola komunikasi, bukan hanya mereka yang terjebak dalam persepsi “muda dan progresif.”
Kepemimpinan yang Berdasarkan Integritas dan Konsistensi
Kepemimpinan yang baik seharusnya berlandaskan pada integritas dan konsistensi. Seperti yang diajarkan dalam tradisi ketimuran kita, seorang pemimpin harus bisa mengenali ketidaksempurnaannya dan berani mengambil keputusan yang sulit, termasuk mengundurkan diri jika dirasa tidak mampu menjalankan tugas dengan baik. Jika kita mengingat tradisi Jepang, di mana pejabat mengundurkan diri setelah terbukti melakukan kesalahan, kita belajar bahwa kepemimpinan yang baik bukan hanya tentang meraih kemenangan atau kekuasaan, tetapi juga tentang mengakui kegagalan dengan kepala tegak. Sikap mengundurkan diri yang dipilih oleh pejabat di Jepang menunjukkan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap posisi yang diemban. Sebagai contoh, Yasuo Ichikawa mengundurkan diri untuk menunjukkan bahwa ia tidak dapat menjalankan amanah dengan baik, dan hal ini diakui sebagai langkah yang terhormat. Di Indonesia, kita sering kali melihat pejabat yang bertahan meski jelas-jelas tidak mampu, hanya karena alasan politik atau kekuasaan.
Kepemimpinan yang baik membutuhkan ketegasan, integritas, dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan jujur dan transparan kepada publik. Mengundurkan diri ketika merasa tidak mampu adalah sebuah bentuk penghormatan terhadap amanah yang diberikan, dan bukan sebuah kekalahan. Pemimpin yang baik harus berani untuk mengakui ketika mereka tidak lagi mampu menjalankan tugas dengan baik. Begitu pula dalam komunikasi kepresidenan, sosok yang tepat harus dipilih, yang tidak hanya mampu berbicara dengan cepat, tetapi dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab. Keputusan-keputusan yang diambil harus tetap konsisten dan berpegang pada prinsip yang jelas demi kebaikan bangsa.
PROBO DARONO YAKTI
Dosen FISIP Universitas Airlangga dan Menyukai Isu-Isu Kebudayaan



