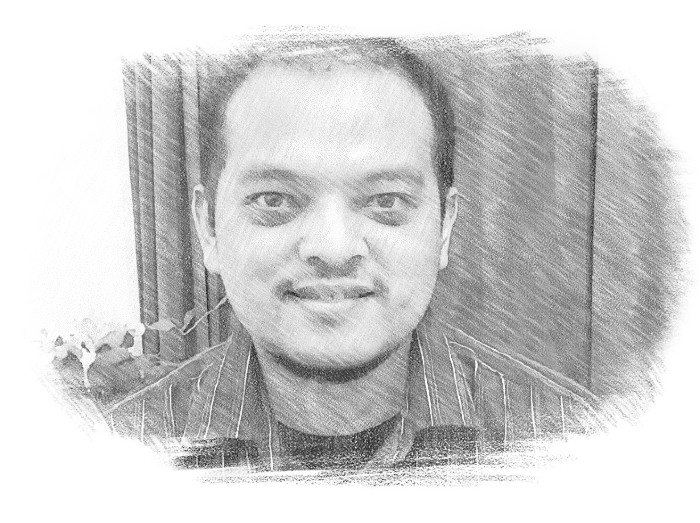Dalam rapat bersama anggota Komisi III DPR RI, pada Senin 4 September 2023, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Rycko Amelza Dahniel mengeluarkan pernyataan kontroversial. Rycko mengusulkan pemerintah harus mengontrol seluruh tempat ibadah dalam rangka penanggulangan radikalisme. Pemerintah harus memiliki mekanisme kontrol terhadap tempat ibadah agar tidak disalahgunakan untuk menyebarkan paham radikalisme. Rycko merujuk kepada pengalaman negara-negara seperti Malaysia, Singapura, beberapa negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Oman, Qatar, serta negara Afrika utara yaitu Maroko dalam hal kontrol terhadap tempat ibadah, orang yang menyampaikan ceramah, serta konten ceramah. Merujuk pada pengalaman negara-negara tersebut, Rycko mengatakan bahwa pemerintah harus mengontrol seluruh tempat ibadah di Indonesia, termasuk mengawasi konten ceramah agama dan siapa yang memberikan materi keagamaan. Rycko mengeluarkan pernyataan tersebut dalam merespon pernyataan dari Safaruddin, anggota komisi III DPR RI, yang mencontohkan masjid milik Pertamina di Balikpapan telah disusupi radikalisme karena setiap hari rajin mengkritik pemerintah.
Pernyataan Rycko, meskipun sebatas usulan, jelas tidak dapat diterima. Pertama, negara tidak pernah menjelaskan definisi secara pasti apa yang dimaksud dengan radikalisme. Berbeda dengan istilah “terorisme” yang memiliki definisi pasti sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, istilah “radikalisme” belum memiliki definisi pasti. Dengan ketiadaan definisi pasti, maka istilah radikalisme rawan digunakan untuk melakukan sekuritisasi terhadap kelompok-kelompok keagamaan yang dianggap berseberangan dengan pemerintah. Ambiguitas definisi radikalisme tercermin dalam pernyataan-pernyataan yang mengindetikkan kritik terhadap pemerintah dengan radikalisme itu sendiri. Ketidakjelasan definsi radikalisme dapat berkonsekuensi pada potensi pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama di tempat ibadah.
Kedua, yang agak janggal, untuk menjustifikasi kontrol terhadap tempat ibadah, Ryco merujuk kepada negara-negara dengan indeks demokrasi yang tidak sempurna. Pada Democracy Index tahun 2022 yang dipublikasikan pada tahun 2023 oleh The Economist, melaporkan bahwa Malaysia merupakan negara dengan Indeks Demokrasi menempati peringkat 40 dunia dengan poin 7.30, diikuti Indonesia di nomor 54 dengan poin 6,71. Sedangkan Singapura menempati urutan 70 dunia dengan poin 6,22. The Economist menyatakan bahwa kategori demokrasi di negara-negara ini adalah “Flawed Democracy.” Sedangkan negara Afrika dan Timur Tengah yang dirujuk Rycko, termasuk dalam kategori “Hybrid Regime” maupun “Authoritarian” yang nilai indeks demokrasinya berada di bawah “Flawed Democracy.” Sebagai contoh, rujukan Rycko yaitu Oman, Qatar, dan Arab Saudi, termasuk negara-negara dalam kategori “Authoritarian” Maroko pun juga termasuk dalam kategori “Hybrid Regime” yang artinya kualitas demokrasi berada jauh di bawah Indonesia. Yang menarik, salah satu indikator dalam mengukur indeks demokrasi adalah “Are all religions permitted to operate freely, or are some restricted? Is the right to worship, permitted both publicly and privately? Do some religious groups feel intimidated by others, even if the law requires equality and protection?” Usulan mengawasi tempat ibadah, jika terlaksana, hanya memperburuk indikator demokrasi Indonesia serta memperburuk citra Indonesia di tingkat internasional. Tokoh agamawan baik dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti Buya Anwar Abbas, maupun dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Gomar Gultom, menyatakan bahwa pernyataan Kepala BNPT sebagai bentuk kemunduran demokrasi.
Ketiga, langkah mengatasi radikalisme maupun terorisme hendaknya berfokus pada akar masalah. Assaf Moghadam, seorang akademisi yang ahli dalam bidang kajian kelompok-kelompok radikal dan studi terorisme, menyatakan bahwa terdapat beberapa kondisi yang menyuburkan fenomena terorisme. Ketimpangan sosial-ekonomi, deprivasi relatif, pengangguran, kegagalan pemerintah untuk menyediakan layanan dasar bagi rakyatnya serta ketidakberdayaan negara mengontrol teritori menjadi penyebab munculnya fenomena terorisme. Selain itu, menyatakan bahwa represi pemerintah dan pengingkaran terhadap hak asasi manusia justru memperbesar kemungkinan terjadinya fenomena terorisme. Terkait dengan hal tersebut, usulan Rycko mengenai kontrol dan pengawasan terhadap tempat ibadah bisa ditafsirkan banyak kalangan sebagai bentuk represi pemerintah terhadap rakyatnya.
Keempat, BNPT kurang cermat mengidentifikasi distribusi radikalisme pada masa kekinian. Materi terkait radikalisme dan terorisme tidak didistribusikan dari tempat ibadah melainkan lebih mudah didapat melalui internet maupun media sosial. Misalnya saja, buku, materi, majalah digital, maupun report mingguan dari kelompok Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) dapat dengan sangat mudah diakses, di-download, bahkan didistribusikan di dunia maya hingga saat ini. Maka tidak heran, misalnya, jika di internet kita dapat menemukan teks baiat kepada khalifah ISIS yang baru diangkat beberapa waktu lalu. Di media sosial pula, kita juga dapat menemukan ucapan selamat Idul Fitri dari ISIS kepada para simpatisannya di Indonesia. Berbagai upaya pemerintah yang membatasi materi terkait radikalisme dan terorisme di internet masih lemah, karena materi-materi terkait hal tersebut masih tersebar bebas di internet yang dapat diakses dengan sangat mudah.
Daripada mengeluarkan pernyataan kontroversial yang menimbulkan kegaduhan publik, terlebih di tahun-tahun politik, lebih baik BNPT memperbaiki kinerja internalnya serta meningkatkan koordinasi antar pihak dalam penanganan isu terkait. Misalnya daripada mengusulkan mekanisme kontrol terhadap tempat ibadah, lebih baik BNPT menciptakan mekanisme kerja yang dapat meminimalisir ego sektoral antar instansi dalam proses deradikalisasi di lapangan. Namun yang lebih mendasar dari itu semua, publik layak mempertanyakan mengapa seorang kepala BNPT sampai tercetus ide untuk mengontrol dan mengawasi tempat ibadah ? Apakah jangan-jangan semangat otoritarianisme masih “tertanam” dibawah alam sadar aparat negara?
PRIHANDONO WIBOWO
Dosen Hubungan Internasional FISIP UPN Jawa Timur