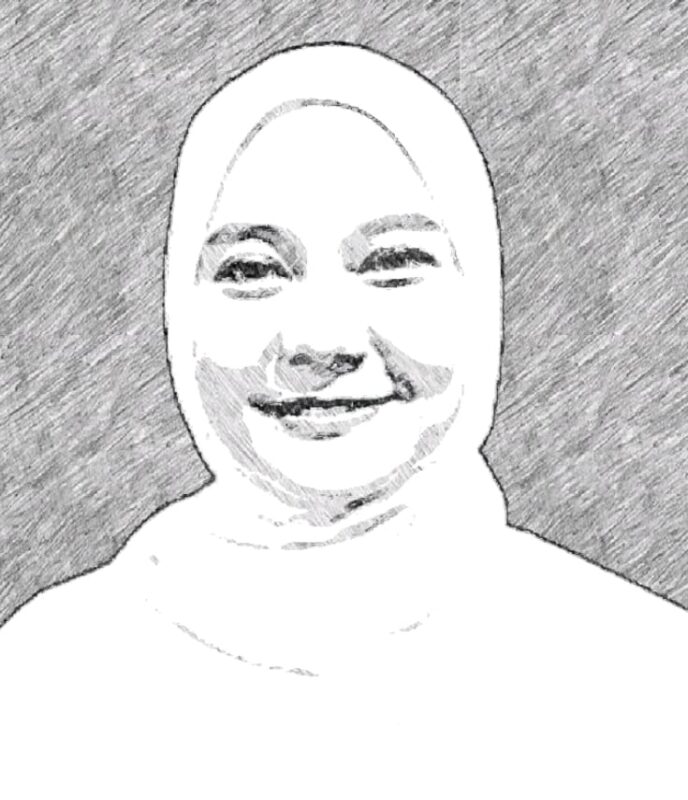
Kenangan terkadang membuat kita ingin kembali ke masa lalu. Menikmati hal-hal indah, mendatangi setiap sudut ruang, benda, atau suasana yang menyenangkan. Ini bukan sekadar romantisme pribadi, melainkan refleksi atas bangunan-bangunan bersejarah yang tampaknya mulai terlupakan saat ini.
Di banyak tempat di Indonesia, mulai dari lereng Gunung Lawu hingga tepian Sungai Musi, kita dapat melihat betapa banyak bangunan yang tak lagi berdiri kokoh. Yang tersisa hanyalah jejak peradaban masa lampau: candi, makam leluhur, hingga benteng kolonial yang menjadi saksi bisu panjangnya perjuangan para pendahulu. Namun, apa yang terjadi kini? Bangunan-bangunan arkeologis itu hanya menjadi situs yang hidup dalam kesepian, nyaris terlupakan, bahkan mungkin suatu saat akan masuk daftar bangunan yang dirobohkan atas nama modernitas.
Bangunan yang dulu menjadi simbol perlawanan dan kekuasaan, kini seolah kehilangan ruhnya. Kita masih dapat melihat fisiknya, tetapi tidak lagi merasakan semangat perjuangan di dalamnya. Teringat peristiwa pembakaran Gedung Negara Grahadi pada 30 Agustus 2025 lalu oleh massa aksi di Surabaya. Gedung itu menyimpan sejarah panjang pemerintahan di Kota Pahlawan. Begitu pula bangunan-bangunan arkeologis lain, seperti Gedung Juang dan rumah adat di Kota Palu, yang kini seolah hanya tinggal dinding tanpa makna.
Fenomena ini bukan semata soal kurangnya perhatian pemerintah atau terbatasnya anggaran konservasi. Ia merupakan cermin cara kita memandang masa lalu, bahkan mungkin tanda bahwa bangsa ini mulai kehilangan arah dalam memahami akar budayanya sendiri.
Berangkat dari perbincangan-perbincangan sebelumnya, tampak bahwa masyarakat kita mulai lupa pada memori perjuangan masa lalu. Sejarawan Prancis Pierre Nora menyebut gejala ini sebagai krisis memori. Dalam karyanya Les Lieux de Mémoire (1984), ia menjelaskan bahwa dahulu ingatan dijaga melalui ritual, tradisi, dan kebiasaan sosial. Kini, ingatan berubah menjadi arsip baik berupa museum, monumen, dan catatan sejarah, yang terpisah dari kehidupan sehari-hari.
Bangunan arkeologis kini resmi berstatus cagar budaya, tetapi sering kali hanya menjadi objek foto wisata. Orang berpose di area candi sekadar untuk unggahan media sosial tanpa ingin tahu nilai spiritual dan sosial masa lampau. Tak jarang, halaman benteng atau gedung juang dijadikan lahan parkir tanpa kesadaran maknanya. Masyarakat tak lagi berinteraksi dengan warisannya sendiri; memori berubah menjadi hiasan tanpa makna.
Modernitas menuntut efisiensi, bukan refleksi. Akibatnya, masa lalu dianggap tidak produktif, tidak menghasilkan uang, tidak menciptakan lapangan kerja, dan tampak tak berguna. Maka, banyak situs arkeologis dibiarkan rusak, tergerus oleh pembangunan jalan atau perumahan. Kita terlalu sibuk menatap masa depan hingga lupa menoleh ke belakang.
Berbicara tentang apa yang layak diingat atau dilupakan, Michel Foucault melalui teori kekuasaan dan pengetahuannya menegaskan bahwa sejarah tak pernah netral. Sejarah berpihak pada mereka yang berkuasa, mereka yang menentukan versi kebenaran dan kenangan. Dalam The Archaeology of Knowledge (1969), Foucault menulis bahwa setiap masyarakat memiliki “rezim kebenaran” sendiri, yakni sistem yang menentukan apa yang boleh diketahui, diingat, dan dipelajari.
Dalam konteks Indonesia, narasi sejarah sering kali terpusat pada kisah besar seperti Majapahit, Sriwijaya, atau perjuangan kemerdekaan, sementara situs kecil dan lokal diabaikan. Jejak kerajaan kecil di Sulawesi Tengah, situs megalitik di Nias, atau benteng maritim di Maluku, jarang masuk dalam wacana nasional. Ketika sejarah dikendalikan oleh narasi besar, ruang bagi sejarah rakyat dan sejarah lokal akan semakin menyempit.
Inilah bentuk halus kekuasaan yang dimaksud Foucault yang bukan kekerasan fisik, melainkan pengendalian cara berpikir dan mengingat. Dengan melupakan situs-situs tertentu, masyarakat sejatinya diarahkan untuk melupakan sebagian identitasnya sendiri.
Antropolog Amerika Clifford Geertz menekankan pentingnya thick description yakni deskripsi mendalam yang tidak hanya menjelaskan apa yang tampak, tetapi juga makna di balik simbol dan tindakan. Bangunan arkeologis, jika dibaca dengan cara ini, bukan sekadar batu dan bata; ia menyimpan kisah hubungan manusia dengan alam, sistem nilai, dan ekspresi spiritual yang membentuk identitas kolektif.
Sayangnya, banyak situs arkeologis di Indonesia kehilangan hubungan itu. Komunitas lokal sering tidak dilibatkan dalam pelestarian. Candi, benteng, atau rumah adat menjadi “benda museum” yang dijaga birokrasi, bukan masyarakatnya sendiri. Maka, makna simbolik pun hilang.
Beberapa benteng di Sulawesi Tengah yang dulunya pusat pertemuan antar budaya kini menjadi tempat tinggal sementara atau dibiarkan terbengkalai. Di banyak tempat, warga bahkan tak tahu bahwa reruntuhan di desanya adalah situs bersejarah. Dalam keadaan demikian, pelestarian mustahil hidup. Sebab tanpa partisipasi sosial, warisan budaya hanyalah artefak mati.
Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita perlu menghidupkan kembali fungsi sosial bangunan arkeologis dengan menjadikannya ruang dialog dengan masa lampau, ruang publik tempat belajar, atau laboratorium budaya.
Kedua, kita perlu membangun narasi alternatif dari bawah. Sejarah lokal harus diangkat, bukan hanya untuk kebanggaan daerah, melainkan juga untuk memperkaya mozaik identitas nasional. Pendekatan “arkeologi pengetahuan” ala Foucault dapat membantu menggali lapisan cerita terpendam tentang rakyat kecil, ritual, atau teknologi tradisional yang terlupakan.
Ketiga, tumbuhkan kesadaran budaya yang reflektif (cultural mindfulness). Artinya, kita tidak hanya bangga terhadap warisan, tetapi juga memahami maknanya dalam konteks kekinian. Di era digital yang serba cepat, kesadaran ini penting agar manusia tidak sepenuhnya dikuasai algoritma dan konsumerisme.
Bangunan arkeologis yang terlupakan di Indonesia adalah metafora tentang cara kita memperlakukan sejarah. Kita membangun gedung tinggi, tetapi membiarkan fondasi peradaban retak. Kita mengingat kemerdekaan, namun melupakan kebudayaan yang melahirkannya.
Pierre Nora mengingatkan bahwa tempat ingatan hanya hidup jika masyarakat masih mengingatnya. Foucault mengajarkan bahwa kekuasaan menentukan apa yang layak diingat. Dan Geertz menegaskan bahwa budaya hanya hidup jika ditafsirkan dengan makna.
Maka, jika kita ingin menjadi bangsa besar, langkah pertama bukanlah membangun lebih banyak gedung, melainkan belajar mengingat lebih dalam. Sebab bangsa yang kehilangan ingatan, sejatinya sedang berjalan tanpa arah, di atas reruntuhan kebesarannya sendiri.
RISMA ARIYANI
Mahasiswa Doktoral FISIP Universitas Airlangga



