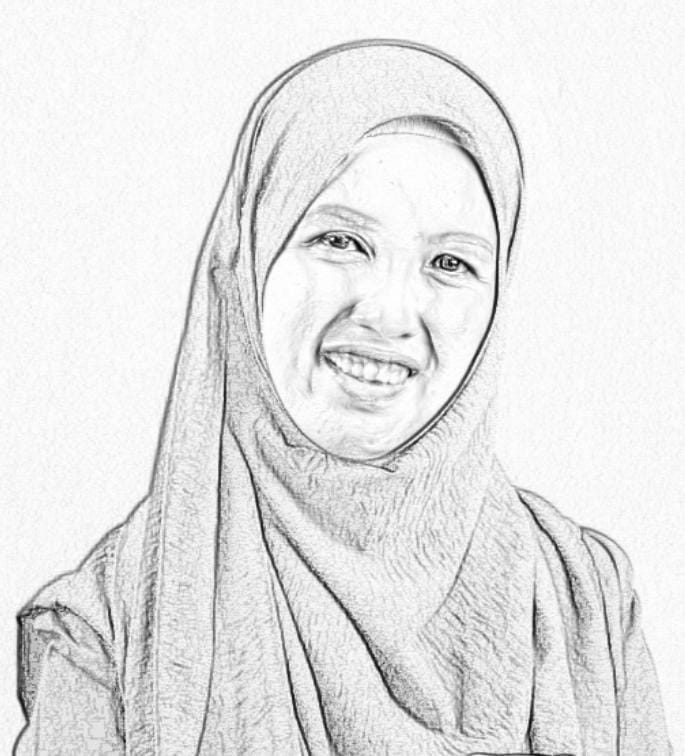
Gelombang dukungan publik untuk korban bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan kuatnya solidaritas masyarakat Indonesia. Dalam hitungan jam, sejumlah figur publik terjun langsung ke lokasi dan memanfaatkan platform crowdfunding yang kini menjadi infrastruktur sosial baru dalam merespons krisis. Zaskia Adya Mecca, misalnya, bersama rekan-rekannya terbang langsung ke daerah terdampak untuk membagikan logistik sekaligus mempublikasikan kondisi terkini.
Pada saat yang sama, Ferry Irwandi berhasil menggerakkan publik melalui Kitabisa (dot com) dan menghimpun donasi hingga Rp 10 miliar hanya dalam waktu satu hari satu malam. Fenomena ini memperlihatkan wajah baru filantropi Indonesia yang semakin digital, personal, dan dipengaruhi figur publik.
Dalam kajian komunikasi bencana, kecepatan penyebaran informasi merupakan unsur penting. Publik membutuhkan informasi yang akurat, real time, dan kredibel. Namun dalam banyak peristiwa, informasi dari pemerintah kerap datang terlambat atau terkesan terlalu teknokratis. Kekosongan itu kemudian diisi oleh figur publik yang berperan sebagai komunikator bencana.
Ketika Zaskia Adya Mecca mengunggah kondisi pengungsian melalui media sosial, publik tidak hanya menerima fakta, tetapi juga empati. Visual dan narasi personal jauh lebih mudah menggugah emosi dibanding rilis resmi pemerintah yang bersifat impersonal. Komunikasi bencana di era digital tidak lagi hanya milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau pemerintah, tetapi juga milik individu-individu yang memiliki jaringan sosial kuat.
Fenomena ini menunjukkan pergeseran peran dari pemerintah sebagai komunikator utama, menjadi figur publik sebagai amplifier informasi dan pemantik aksi sosial. Peran baru ini efektif karena mereka beroperasi dalam sistem komunikasi yang informal, responsif, dan dekat dengan keseharian warganet.
Filantropi Digital: Perjumpaan antara Kepercayaan dan Kecepatan
Indonesia secara konsisten menempati peringkat atas dalam “World Giving Index”, menandakan tingginya semangat filantropi masyarakat. Tradisi tolong-menolong menjadi fondasi sosial yang terus bertahan, bahkan semakin menguat melalui teknologi digital.
Namun filantropi digital tidak semata berkaitan dengan teknologi, melainkan juga kepercayaan. Publik berdonasi bukan hanya karena iba terhadap kondisi korban, tetapi karena percaya kepada penggalang dana. Kepercayaan inilah yang membuat kampanye Ferry Irwandi mampu menembus Rp 10 miliar dalam waktu singkat. Publik merasa yakin dana yang mereka sisihkan akan disalurkan secara tepat, transparan, dan cepat.
Ketika kepercayaan terhadap institusi formal melemah, kepercayaan kepada figur publik yang dianggap tulus dan tidak birokratis justru meningkat. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana modal sosial seseorang dapat berubah menjadi modal filantropi. Figur publik menjadi jembatan antara empati publik dan penyaluran bantuan.
Derasnya dukungan publik melalui kanal non pemerintah tidak terlepas dari konteks kekecewaan masyarakat terhadap penanganan bencana oleh pemerintah. Gerak cepat figur publik sering terbaca sebagai perbandingan yang sulit dihindari. Publik melihat respons semi informal yang lebih sigap, responsif, dan berempati dibandingkan alur birokrasi yang kerap lamban.
Terdapat tiga indikator kekecewaan publik yaitu pertama, kecepatan bantuan non pemerintah mengungguli bantuan pemerintah. Kedua, ruang digital dipenuhi kritik dan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah. Ketiga, keberhasilan pengumpulan dana besar dalam waktu singkat menunjukkan bahwa masyarakat lebih mempercayai jalur alternatif.
Kekecewaan ini tidak berarti seluruh kinerja pemerintah buruk, tetapi mencerminkan kesenjangan antara ekspektasi publik dan kapasitas penanganan birokrasi. Ketika masyarakat menilai pemerintah tidak hadir secara memadai, mereka mengambil alih peran itu melalui self-organized response.
Ada ironi yang perlu dicermati lebih dalam. Di satu sisi, kita patut bangga pada solidaritas publik serta gerak cepat figur publik. Namun di sisi lain, ketergantungan yang berlebihan kepada figur publik dapat menjadi sinyal lemahnya tata kelola bencana.
Jika masyarakat terlalu mengandalkan crowdfunding dan jaringan personal, keberlanjutan penanganan jangka panjang menjadi tidak stabil. Bencana tidak hanya membutuhkan bantuan logistik sesaat, tetapi juga pemulihan infrastruktur, trauma healing, pembangunan rumah, hingga perencanaan mitigasi untuk masa depan. Semua itu memerlukan peran negara yang kuat dan terstruktur. Fenomena ini seharusnya dibaca sebagai alarm bahwa sistem formal perlu berbenah agar tidak selalu “dikalahkan” oleh inisiatif publik yang spontan.
Filantropi digital dan keterlibatan figur publik bukanlah sesuatu yang perlu dipandang negatif. Sebaliknya, ini merupakan peluang untuk membangun ekosistem penanggulangan bencana yang lebih kolaboratif. Pemerintah perlu melibatkan figur publik sebagai mitra komunikasi bencana, bukan untuk menggantikannya, melainkan untuk memanfaatkan jangkauan dan kecekatan mereka sebagai kanal resmi kedua.
Pemerintah harus mampu menyajikan data real time melalui platform yang mudah diakses dan dipahami. Platform crowdfunding dapat diposisikan sebagai pelengkap strategi penanganan bencana. Dengan regulasi yang jelas, crowdfunding dapat menjadi instrumen yang sinergis dengan program bantuan resmi.
Koordinasi lintas sektor harus dioptimalkan. Pemerintah, NGO, sektor swasta, figur publik, dan komunitas lokal perlu berada dalam satu ekosistem respons yang terhubung. Sinergi ini pada akhirnya tidak hanya memperkuat mitigasi bencana, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap negara.
Solidaritas Publik sebagai Kapital Sosial Bangsa
Bencana di Sumatera kembali mengingatkan bahwa kekuatan terbesar bangsa ini adalah solidaritas warganya. Dalam situasi yang paling sukar sekalipun, masyarakat Indonesia selalu menemukan cara untuk hadir bagi sesama. Namun solidaritas publik tidak boleh menjadi alasan negara lengah.
Kehadiran figur publik dan platform digital dalam penanganan bencana adalah cerminan transformasi sosial kita. Fenomena ini mengandung unsur empati, perkembangan teknologi, sekaligus kritik publik terhadap negara. Jika pemerintah mampu membaca fenomena ini secara jernih, ia dapat menjadikannya momentum untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana yang lebih humanis, responsif, dan berkeadilan.
Pada akhirnya, bencana tidak boleh hanya menyisakan puing-puing. Ia harus menghadirkan pelajaran. Salah satunya adalah bahwa negara dan masyarakat perlu berjalan beriringan, bukan saling mengisi kekosongan. Solidaritas warga adalah kekuatan besar, tetapi negara tetap harus menjadi jangkar utama ketahanan bencana di Indonesia. Semoga.
RATNA PUSPITA SARI
Mahasiswi Program Doktoral FISIP Universitas Airlangga



