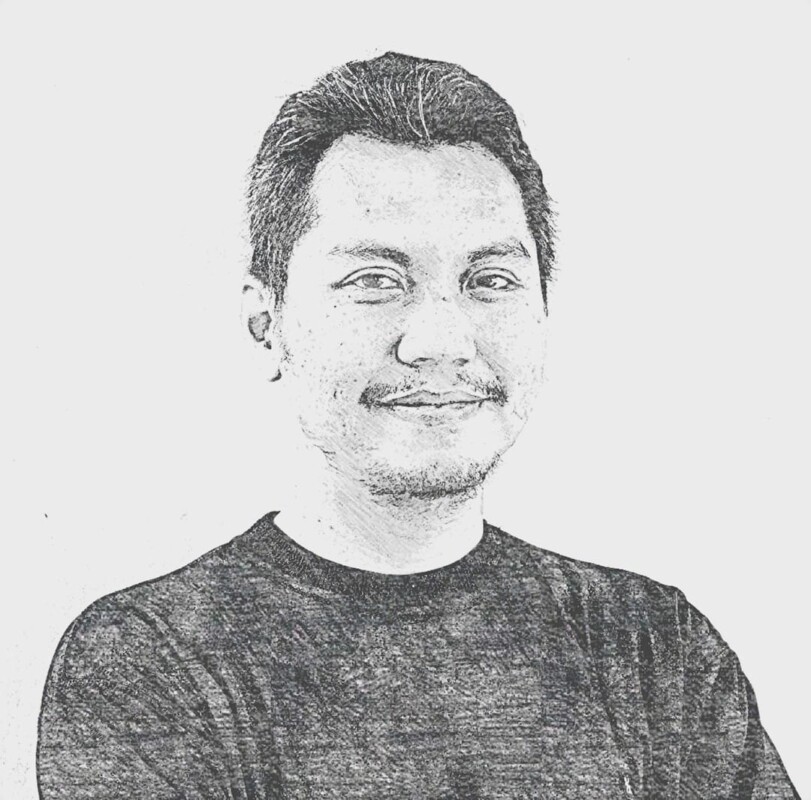
Pasti sudah banyak artikel mengenai refleksi kemerdekaan bangsa kita, Indonesia. Tentu tidak sedikit juga telaah kritis di media massa akan momentum ini. Nah, mari kita tambah satu semuanya. Melalui tulisan ini, penulis mengajak pembaca untuk sedikit kritis dan sejenak merenung. Tulisan ini dibagi menjadi tiga bagian, yakni 1) apa itu merdeka dan kenapa menjadi merdeka itu penting, 2) merdeka tapi apakah bijaksana, 3) merdeka, tapi jangan semaunya.
Sesudah meniup terompet, menyalakan kembang api, atau mengunggah sorak sorai tujuh belasan di media sosial, mari kita bertanya kemudian, apa itu merdeka? Apa benar kita sudah merdeka? Tanyakan kembali jika sudah menemukan arti harafiah dari kata “merdeka”. Apakah kita sudah bebas? Apakah kita sudah kuat, makmur, sejahtera, dan berkedilan sosial? Terkadang pertanyaan-pertanyaan seperti itu bertebaran di banyak tulisan, ceramah keagamaan, sampai sambutan acara tirakatan kemerdekaan di kampung dan desa. Tapi, tidak jamak individu maupun kelompok yang menggaungkan terus pertanyaan-pertanyaan itu. Bagi penulis, banyak dari kita yang masih “belum merdeka” dalam ritus pemikiran bahwa kemerdekaan kita “hanyalah sebuah perayaan”. Begitu juga dengan diri penulis, contohnya, yang “belum merdeka” dari kekhawatiran akan masa depan masyarakat kelas menengah ke bawah di Indonesia. PHK, perundungan, ketidakadilan, konsumsi berlebihan, dan tanah yang digadaikan adalah sumber keyakinan saya bahwa kita “belum merdeka”. Bukankah definisi bebas dari penjajahan sudah milik zaman perjuangan pergerakan kemerdekaan? Apa iya kita masih menggunakan definisi merdeka yang sama untuk generasi yang tugas utamanya adalah mengisi dan mempertahankan kemerdekaan? Penulis khawatir, kita hanya latah dan salah kaprah karena kita juga sebenarnya resah. Tapi lagi-lagi, resah itu tidak bisa jadi kesadaran kolektif karena kita memang tidak punya “mental dan pikiran yang merdeka secara hakiki”. Kita masih takut, kita masih bohong. Bahkan takut dan bohong adalah mata pelajaran intrinsik yang terkadang diturunkan secara tradisi di lembaga pendidikan formal.
Bukankah kita takut bertanya saat di kelas sekolah karena ada ancaman sanksi kalau kita salah? Sejak kapan kita diajarkan di sekolah untuk menghargai, menghormati, dan bahkan menganggap alam sebagai ekosistem kehidupan yang integral? Justru mungkin belenggu untuk merdeka berpikir itu sudah dibentuk sejak dari bangku sekolah. Tidak jarang bukan anak yang sedikit berbeda dengan teman-teman lainnya justru termarjinalisasikan? Bukankah dalam mengisi kemerdekaan kita diminta untuk memahami perbedaan? Apapun itu. Kemerdekaan bukan berarti harus selalu benar dan tanpa keberanian. Kemerdekaan adalah berproses menuju kebenaran dengan modal keberanian. Kemerdekaan juga menjadi hasil dari tumbuhnya kebijaksanaan yang organik dari masyarakat. Pada kasus apapun dan di belahan bumi manapun, tidak ada kemerdekaan yang dicapai tanpa proses menuju kebenaran atau dengan modal ketakutan.
Sudah merdeka seharusnya makin bijaksana sebuah negara dan warganya. Sudah merdeka seharusnya tidak makin semaunya. Kita diturunkan melalui generasi manusia yang dekat dengan alam, yang menganggap alam adalah sendi dan pembuluh darah jagad semesta. Alam merupakan cerminan keseimbangan semesta yang harus dirawat dan terus diusahakan lestari. Tapi saat ini sepertinya alam bukan jadi sahabat lagi. Pada masa yang disebut oleh Crutzen dan Stoermer sebagai Antroposen, alam seakan hanya menjadi komoditas yang bisa dieskploitasi secara ekonomi dengan iming-iming keuntungan tanpa batas. Walaupun sudah dipertandingkan dengan konsep “Ekonomi Donat” oleh Kate Raworth dan diskursus “Paradoks Keberlanjutan” oleh Gita Wirjawan, rasanya Indonesia semakin jauh dari keberpihakan terhadap alam. Banyaknya kasus tambang ilegal di Jawa Tengah, permasalahan sampah di Jawa Barat-Jawa Timur-Bali, banjir di Samarinda dan Demak, belum lagi pembersihan hutan akibat proyek pembangunan yang ambisius di Kalimantan Timur dan Papua. Bukankah itu cerminan kemerdekaan kita yang semaunya? Mungkin kita semua lupa bahwa keanekaragaman hayati dan biodiversitas Indonesia menjadi yang tertinggi ketiga di dunia di bawah Brazil dan Kolumbia. Indonesia lalu berhak menyandang predikat negara megabiodiversity. Bukankah dengan predikat itu kita seharusnya sadar bahwa senjata paling utama Indonesia bisa jadi adalah biodiversitas. Tapi, bisa jadi, biodiversitas tidak punya daya tawar di hadapan nafsu keserakahan manusia. Penulis jadi teringat apa yang dinyatakan Mohandas Karamchand “Mahatma” Gandhi tentang bumi dan keserakahan manusia, “Earth provides enough to satisfy every man’s needs, but not every man’s greed.”
Mungkin ada baiknya kita kembali belajar kepada dan bersama alam semesta. Pendidikan formal dan non-formal harus lebih mendekatkan diri kembali dengan alam semesta. Mungkin dengan begitu tidak hanya pikiran dan analisis manusia yang semakin tajam, tapi juga perasaan manusia yang juga akan mengambil peran. Berbeda dengan romantisasi, mendekatkan diri kepada dan bersama alam semesta tidak harus menjalani kehidupan mundur ke belakang. Dengan demikian, antroposen tidak hanya akan dipenuhi oleh keserakahan, tapi juga ditandingkan dengan kebijaksanaan. Paling tidak, orang Indonesia yang merdeka tidak akan semaunya juga. Apa manfaatnya manusia merdeka, berpendidikan, dan terpelajar berkumpul di Jakarta atau Surabaya jika udara sudah tidak sehat, banjir tak kunjung teratasi, dan permukiman kumuh masih menjadi pernak-pernik kota terbesar di Indonesia?
Terakhir, jika pendidikan seharusnya memerdekakan kita, tapi kenapa kita masih saja semaunya? Jangan-jangan pendidikan kita yang selama ini lupa membuat kita untuk tetap menghargai dan merangkul jagad alam semesta? Jangan-jangan pendidikan kita yang selama ini membuat kita menjadi makhluk yang semaunya? Kalau bukan, maka buktikan.
PRAJA FIRDAUS
Pegiat Lingkungan dan Pendiri Yayasan Abyakta Acitya Bhumi



