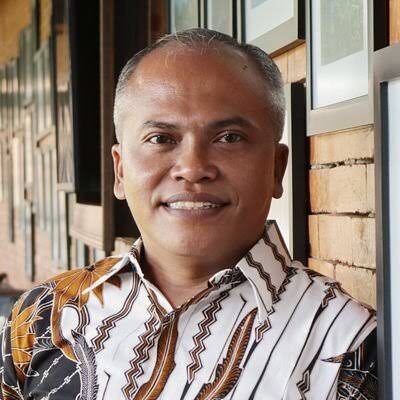
“Ketika senyap digantikan oleh sirene, dan pengawasan digantikan oleh penguasaan, maka yang tumbuh bukan ketertiban, melainkan ketakutan yang teratur”.
Tulisan ini merupakan tanggapan atas editorial Tempo edisi 23 Maret 2025 berjudul “Tahu-tahu Dwifungsi Polri”, yang menyoroti penempatan perwira tinggi polisi aktif di jabatan sipil sebagai potensi bahaya baru dalam tata kelola keamanan dan pemerintahan sipil kita.
Banyak poin dalam editorial tersebut patut diapresiasi, tetapi ada beberapa hal yang perlu diluruskan dan diperdalam agar publik tidak terjebak pada kesimpulan yang menyederhanakan.
Fenomena Lama yang Tak Pernah Dituntaskan
Anggapan bahwa publik baru menyadari maraknya perwira Polri mengisi jabatan sipil setelah mutasi besar-besaran pada 12 Maret 2025 kurang akurat. Fenomena ini jelas bukan barang baru. Sejak periode pertama Presiden Joko Widodo, penempatan polisi aktif di luar struktur Polri telah menjadi perhatian banyak kalangan.
Saya, Bambang Rukminto, dan lembaga tempat kami bernaung, ISESS, misalnya, konsisten menyuarakan keprihatinan ini dalam berbagai forum dan media. Sayangnya, isu ini jarang mendapat perhatian serius. Ia kerap kalah gaung dibanding isu dwifungsi militer dan tak jarang larut dalam narasi pembenar yang menyesatkan.
Pangkal masalahnya pun bukan sekadar soal “perwira Polri banyak nganggur”. Argumen semacam itu justru menyederhanakan persoalan dan mengalihkan perhatian dari akar masalah yang lebih serius: luasnya kewenangan dan pengaruh Polri, terutama dalam ranah penegakan hukum.
Posisi strategis inilah yang membuat perwira tinggi Polri menjadi incaran dan rebutan. Maka terbentuklah simbiosis mutualisme antara elite politik dan elite kepolisian: saling menggoda, saling memanfaatkan, dan saling menopang. Pola ini bukan baru muncul hari ini, tetapi sudah mulai terbentuk sejak menjelang Pemilu 2004 dan terus berulang, terutama saat momen politik krusial.
Dari ABRI ke Negara Polisi: Cermin Sejarah yang Terabaikan
Kecenderungan Polri berekspansi ke wilayah kekuasaan sipil menandai kembalinya pola lama yang dulu dijalani dalam struktur ABRI. Jangan lupa, Polri adalah bagian dari ABRI selama puluhan tahun. Ia menjadi bagian dari mesin politik negara yang mengontrol penuh ranah sipil.
Setelah dipisahkan dari TNI pasca-reformasi, Polri memang menjadi lembaga tersendiri. Tapi secara kelembagaan, warisan konsep ruler-appointed police—yakni kepolisian yang ditentukan dan dikendalikan oleh penguasa—masih kuat membekas. Hal ini membuat Polri sulit menjaga jarak dari kekuasaan, apalagi bila kontrol sipil dan mekanisme akuntabilitasnya lemah.
Satu anomali penting justru terjadi pada penghujung masa jabatan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Ketika itu, Kapolri Jenderal Suroyo Bimantoro menolak diberhentikan oleh Presiden dan justru berseberangan dengan Kepala Negara.
Ironisnya, pembangkangan itu bukan dikoreksi, melainkan jadi momentum politik untuk mempercepat lengsernya Gus Dur. Setelahnya, loyalitas Polri pada penguasa memang nyaris tak pernah terganggu. Tapi peristiwa itu mestinya jadi pengingat penting betapa rapuhnya relasi kuasa bila Polri dibiarkan terlalu dekat dengan lingkar kekuasaan.
Editorial Tempo juga menyinggung soal kecemburuan militer terhadap maraknya perwira polisi di jabatan sipil. Bisik-bisik kegelisahan soal itu memang ada. Namun menjadikannya seolah-olah alasan penting di balik revisi UU TNI adalah penyederhanaan yang bisa menyesatkan nalar publik.
Revisi UU TNI tidak semata-mata dipicu oleh kecemburuan antar aparat bersenjata, melainkan oleh kebutuhan objektif: pembenahan fungsi pertahanan dan koreksi praktik-praktik sebelumnya yang keluar dari rel relasi sipil-militer yang sehat.
Superbody dan Ancaman terhadap Kebebasan Sipil
Yang lebih perlu menjadi perhatian hari ini adalah bagaimana Polri kian hari kian menjelma menjadi superbody—lembaga superkuat yang tak hanya dominan dalam penegakan hukum, tetapi juga masuk ke ranah intelijen, ruang siber, dan bahkan yurisdiksi global.
Naskah akademik dan draf revisi UU Polri yang diusulkan DPR RI dengan gamblang memperlihatkan ambisi itu. Kewenangan Polri akan mencakup penindakan semua tindak pidana, pengawasan ruang digital, hingga pengerahan kekuatan di luar negeri. Ini adalah bentuk sentralisasi kekuasaan penegakan hukum yang berbahaya bagi sistem demokrasi.
Sejarah menunjukkan bahayanya konsentrasi kekuasaan semacam itu. Model ABRI di masa Orde Baru memperlihatkan bagaimana kekuasaan bersenjata yang masuk ke ranah sipil, alih-alih menciptakan stabilitas, justru memunculkan stagnasi dan represi.
Praktik kepolisian kolonial Hindia Belanda juga menjadi cermin bahwa ketika institusi kepolisian tak tunduk pada prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil, mereka akan mudah berubah menjadi alat represi kekuasaan terhadap rakyatnya sendiri.
Kini, ketika Polri berpotensi memperluas pengaruhnya ke berbagai ranah, kita seolah sedang mengulang dua babak sejarah tersebut sekaligus—tetapi dengan wajah regulatif yang sah dan legal-formal.
Polri juga menghadapi dilema struktural yang rumit. Sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus penegak hukum, Polri ditempatkan dalam posisi ambivalen: harus tunduk pada kontrol demokratis, namun juga harus independen dari intervensi kekuasaan.
Jika tidak ada batas dan kontrol yang kuat, maka celah ini akan dengan mudah dimanfaatkan—baik oleh kekuasaan maupun (dan ini yang lebih berbahaya) oleh aparat itu sendiri. Perluasan kewenangan Polri yang tidak dibarengi dengan reformasi internal, penguatan akuntabilitas, dan penegakan kontrol sipil yang kokoh hanya akan memperbesar ancaman terhadap kebebasan sipil.
Dan perlu diingat, senjata Polri yang paling berbahaya bukanlah senjata api, melainkan kewenangannya sebagai alat penegak hukum. Kewenangan itulah yang memungkinkan pembungkaman, kriminalisasi, bahkan pengabaian terhadap rasa keadilan warga negara. Apalagi bila para pemegang kewenangan tersebut tidak mampu menjaga profesionalisme dan integritas.
Demokrasi di Persimpangan
Reformasi sektor keamanan yang diperjuangkan sejak 1998 dilandasi satu prinsip penting: supremasi sipil atas kekuatan bersenjata. Itu sebabnya TNI dibatasi pada fungsi pertahanan, sementara Polri pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta penegakan hukum.
Ketika batas itu dilanggar—oleh siapa pun—maka demokrasi sedang dalam ancaman. Ketika elite sipil membiarkannya, bahkan memanfaatkannya demi kekuasaan atau sekadar keuntungan elektoral, maka kita sedang mengkhianati reformasi.
Maka, tugas masyarakat sipil hari ini bukan hanya mencegah kembalinya dwifungsi militer, tetapi juga menghentikan ekspansi Polri ke ranah-ranah yang bukan kewenangannya. Jangan tunggu sampai dominasi itu menjelma menjadi otoritas mutlak. Sebab ketika negara polisi benar-benar hadir, maka bukan hanya kebebasan warga yang terancam—tapi juga masa depan demokrasi, supremasi sipil, bahkan kekuasaan itu sendiri.
—
KHAIRUL FAHMI
Pemerhati Masalah Hankam
Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS)



