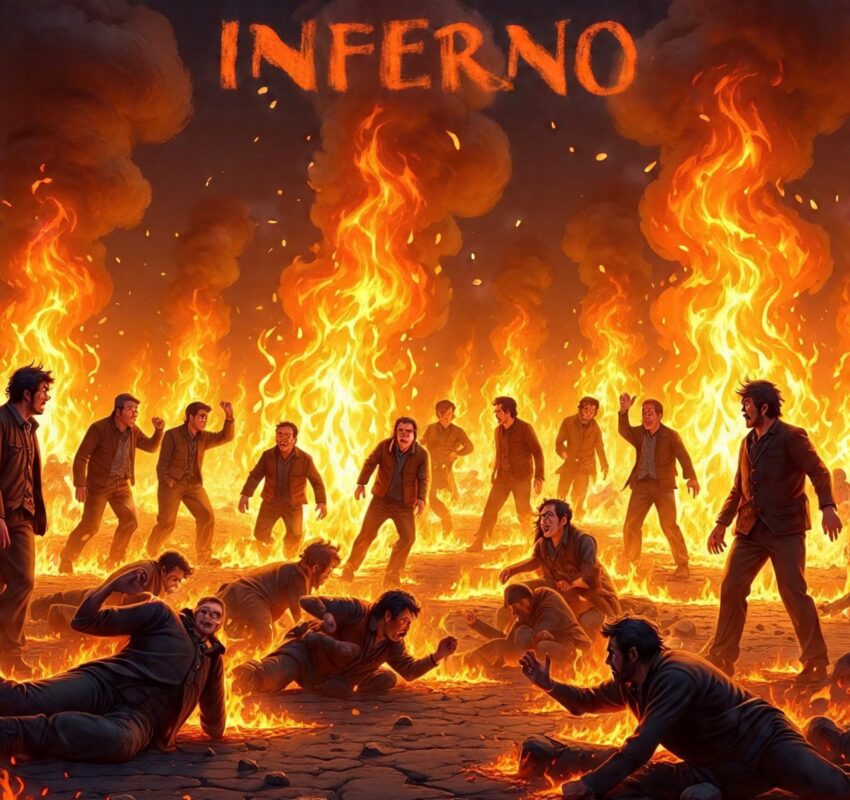
“Yang numinus adalah yang lain secara keseluruhan, sebuah misteri yang menakutkan sekaligus mempesona (mysterium tremendum et fascinans).” — Rudolf Otto (1869-1937), The Idea of the Holy (Jerman 1917; Inggris 1923)
Merefleksikan humanisme dan kebangsaan di tengah deras tantangan “agama digital“ global alaf-21 ini, tulisan Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila (2011) dari Dr. Yudi Latif (61), patut dirujuk untuk menimbang ulang tafsirnya atas Sila Pertama Pancasila: “Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Ia menolak pendekatan yang memisahkan antara ketuhanan dan kebudayaan, dan justru menegaskan bahwa sila pertama harus dimaknai sebagai “Ketuhanan yang Berkebudayaan.”
Tafsir ini bukan sekadar semantik, melainkan sebuah gagasan filosofis yang menempatkan sakralitas sebagai fondasi kehidupan kebangsaan Indonesia.
Dalam pandangan Latif, Ketuhanan tidak hadir sebagai dogma yang membeku, melainkan sebagai nilai transenden yang menjiwai praksis budaya, etika sosial, dan struktur kenegaraan.
Ia berhadapan langsung dengan sekularitas yang dipasok dari filsafat idealisme Hegel, yang cenderung menempatkan negara sebagai manifestasi tertinggi dari akal universal, dan menggeser ruang sakral ke pinggiran kehidupan publik.
Mengacu pada Phänomenologie des Geistes (1807; LKiS,2007), Georg Wilhelm Friedrich Hege l(1887-1831), menulis, “Spirit adalah aktualitas etis suatu bangsa; ia adalah diri suatu masyarakat sebagai diri yang nyata.”
Gagasan ini menempatkan roh (Geist) sebagai entitas etis dan historis yang hidup dalam kebudayaan dan institusi suatu bangsa.
Roh bukan sekadar kesadaran individual, melainkan kesadaran kolektif yang mengandung nilai-nilai luhur, termasuk gagasan suci yang menjiwai kehidupan sosial dan politik.
Sakralitas dalam pemikiran Hegel bukanlah dogma religius, melainkan bentuk kesadaran etis yang berkembang melalui sejarah dan praksis budaya.
Gagasan suci menurut Hegel hadir sebagai pengalaman dialektis, di mana kesadaran manusia berkembang dari bentuk yang paling sederhana menuju pengenalan akan kebebasan dan akal universal.
Dalam proses ini, nilai-nilai transenden seperti keadilan, kebajikan, dan ketuhanan menjadi bagian dari struktur etis masyarakat.
Sakralitas bukanlah sesuatu yang statis, tetapi hasil dari perjuangan kesadaran menuju pengenalan diri yang utuh dalam sejarah.
Memasuki usia delapan puluh tahun kemerdekaan, Indonesia tampak mengalami kemerosotan nilai-nilai suci yang dahulu menjadi roh kebangsaan.
Sakralitas yang dulu menjadi sumber inspirasi dan pengikat moral kini tergantikan oleh kalkulasi pragmatis dan retorika identitas yang dangkal.
Ketuhanan yang Berkebudayaan, sebagaimana digagas Latif, bukan sekadar pengakuan formal atas pluralitas agama, tetapi sebuah panggilan untuk menjadikan nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber etika publik yang hidup dalam kebudayaan.
Dalam konteks dan kontestasi ini, kebudayaan bukan sekadar ekspresi estetis, melainkan medan artikulasi nilai-nilai transenden yang membentuk manusia sebagai makhluk bermoral dan berkomunitas.
Mengutip Rudolf Otto dalam The Idea of the Holy menyebut bahwa pengalaman religius yang otentik selalu mengandung elemen “mysterium tremendum et fascinans”, sebuah daya tarik yang menggetarkan sekaligus mempesona.
Sakralitas bukanlah sesuatu yang dapat direduksi menjadi rasionalitas atau norma sosial, melainkan pengalaman eksistensial yang menghubungkan manusia dengan yang tak terhingga.
Ketika sakralitas ini tidak lagi dihayati dalam kehidupan publik, maka yang tersisa hanyalah ritual kosong dan simbol-simbol yang kehilangan makna.
Harvey Cox (96), teolog dan profesor emeritus di Harvard Divinity School, dalam The Secular City: Secularization and Urbanization in Theological Perspective (1965), jauh hari telah memperingatkan bahwa modernitas yang menyingkirkan sakralitas dari ruang publik akan menghasilkan kota-kota yang efisien namun kehilangan jiwa.
Dalam perspektif kebangsaan kita hari ini -dengan ide sekuler Sumpah Pemuda Oktober 1928- kota-kota tumbuh pesat, teknologi berkembang canggih, tetapi nilai-nilai luhur yang mengikat manusia sebagai bangsa mulai memudar, baik daring maupun luring.
Clifford Geertz (1926-2006) dalam The Interpretation of Cultures (1972; Kanisius 1992) menekankan bahwa budaya adalah sistem makna yang diartikulasikan melalui simbol-simbol yang hidup dalam praktik sosial.
Ia mengulas, “Budaya bukanlah sebuah kekuatan, sesuatu yang menjadi sebab terjadinya peristiwa, perilaku, lembaga, atau proses sosial; budaya adalah sebuah konteks, sesuatu yang di dalamnya peristiwa, perilaku, lembaga, atau proses tersebut dapat dijelaskan secara masuk akal—dengan kata lain, secara mendalam.“
Ketuhanan yang Berkebudayaan, dalam tafsir Geertz, berarti menjadikan nilai-nilai ketuhanan sebagai sistem makna yang dihidupi dalam tindakan, bukan sekadar dikutip dalam pidato.
Ia harus hadir dalam cara kita memperlakukan sesama, dalam cara kita membangun institusi, dan dalam cara kita merawat bumi sebagai ciptaan yang suci.
Tanpa itu, kebudayaan hanya menjadi kulit luar, sebuah “outward appearance“ yang kehilangan kedalaman spiritualnya.
Lebih jauh, Dante Alighieri (1265-1321) dalam Inferno (Divina Commedia, 1314), menulis jiwa-jiwa yang tersesat tidak dihukum karena kejahatan besar, tetapi karena kehilangan orientasi spiritual.
Dikutip:, “e quindi uscimmo a riveder le stelle” (dan dari sana kami keluar untuk kembali melihat bintang-bintang) menjadi simbol kuat dari kelahiran kembali, harapan, dan awal perjalanan spiritual menuju penyucian. Ini adalah transisi dari metafora kegelapan moral (Inferno) menuju pembersihan jiwa (Purgatorio).
“Jiwa-jiwa“ tersesat adalah cermin dari masyarakat yang kehilangan gagasan suci, yang hidup dalam rutinitas tanpa arah, dan yang menukar sakralitas dengan kenyamanan “flexing“ duniawi.
Indonesia hari ini, dengan atau tanpa efisiensi, Danantara, MBG, Kordes dan janji-janji kemakmuran, jika tidak segera menghidupkan kembali Ketuhanan yang Berkebudayaan, berisiko menjadi bangsa yang tersesat di lorong inferno sejarah.
Bergerak cepat mirip kereta Whoosh bersama tagihan utang, tanpa arah, hidup tanpa makna, dibakar oleh api sekularisme dan kehilangan roh kebangsaan yang, dahulunya, menjadi sumber kekuatannya, tanda-tanda di labirin inferno akan cepat bereskalasi.
Karena itu, gagasan suci bukanlah nostalgia ideologis, melainkan kompas moral yang harus terus diperbarui dan dihidupi sampai kapanpun.
Ketuhanan yang Berkebudayaan adalah panggilan untuk menjadikan sakralitas sebagai sumber nilai, bukan sekadar simbol: ritual dan rutinitas hampa.
Gagasan suci berkebudayaan adalah ajakan untuk membangun bangsa dengan jiwa cantik dan sejuk. Dan bukan hanya dengan tubuh gagah yang kosong cahaya.
Di dunia yang semakin sekuler dengan daya masif digitalisasi, gagasan suci berkebudayaan menjadi lebih penting dari sebelumnya. Sebab tanpa itu, kebudayaan akan kehilangan makna terdalam dan bangsa akan kehilangan arah. Kelak, gampang retak, runtuh dan hancur.
#coversongs: Lagu “Melati Suci.“ Ciptaan Guruh Soekarnoputra (1973) dan versi Tika Bisono dirilis sekitar 1980.
Lagu Melati Suci adalah karya puitis yang diciptakan Guruh Soekarnoputra (72) sebagai bentuk penghormatan kepada ibundanya, Fatmawati (1923-1980), yang dikenal sebagai penjahit bendera pusaka Merah Putih.
Lagu ini menggambarkan kesucian, ketulusan, dan pengorbanan seorang perempuan Indonesia, yang diibaratkan seperti bunga melati, simbol keanggunan dan kesucian dalam budaya Nusantara.
Dalam versi yang dilantunkan oleh Tika Bisono, seorang psikolog dan penyanyi, lagu ini menjadi lebih kontemplatif dan menyentuh, sering dibawakan dalam konteks peringatan Hari Pahlawan atau Hari Sumpah Pemuda.
Liriknya mengandung pesan tentang pengabdian tanpa pamrih, cinta tanah air, dan spiritualitas perempuan Indonesia yang menjadi fondasi kebangsaan.
REINER EMYOT OINTOE (ReO)
Fiksiwan



