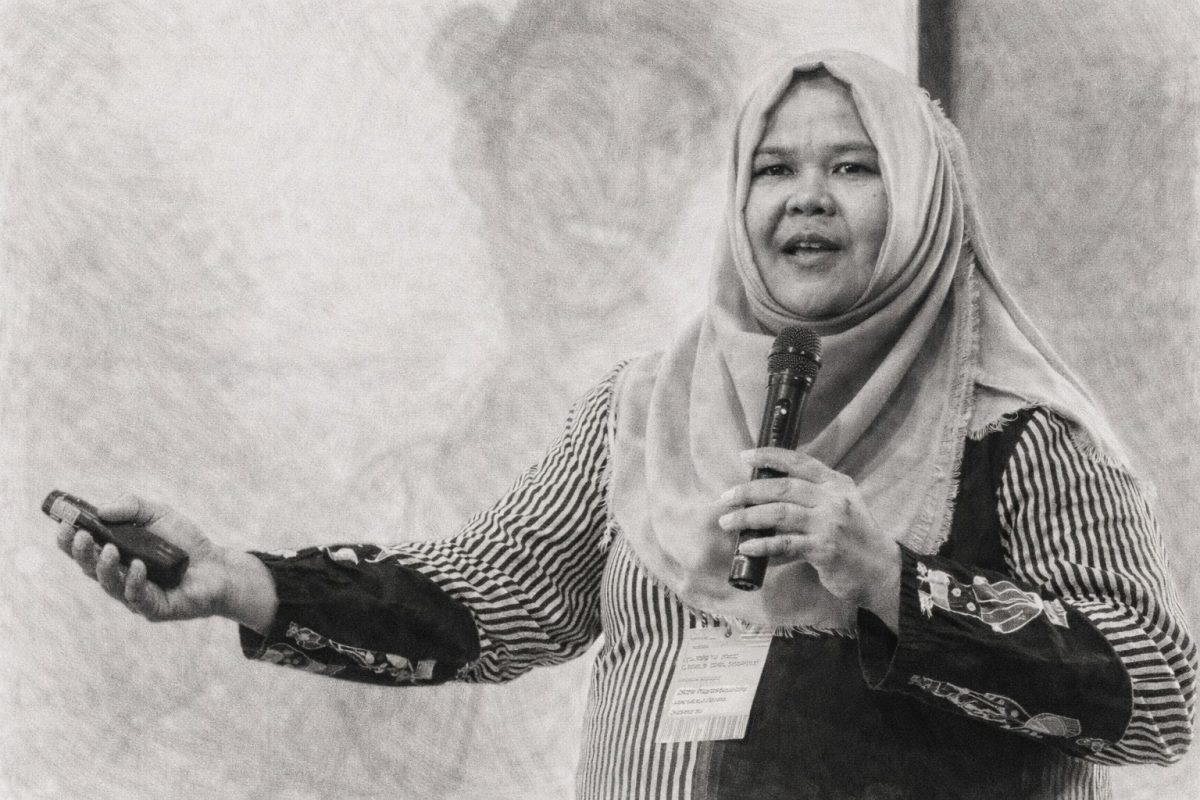
Keengganan pemerintah menetapkan bencana di Sumatera sebagai Bencana Nasional tidak dapat dilepaskan dari kalkulasi politik dan hukum negara. Namun kehati-hatian tersebut tidak boleh terus-menerus disajikan sebagai sikap rasional, terlebih jika berujung pada pengabaian tanggung jawab dasar negara terhadap warganya. Penetapan status Bencana Nasional bukan sekadar pilihan administratif, melainkan keputusan normatif yang mencerminkan keberpihakan negara: apakah negara hadir lebih dahulu bersama korban, atau justru sibuk melindungi dirinya sendiri dari konsekuensi anggaran dan hukum.
Secara hukum, penetapan status Bencana Nasional secara otomatis memindahkan beban tanggung jawab utama kepada pemerintah pusat. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah pusat untuk mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik secara masif. Namun kewenangan tersebut tidaklah netral; ia sekaligus mengandung kewajiban. Begitu status nasional ditetapkan, negara tidak lagi dapat membatasi diri pada peran koordinatif atau bantuan tambahan, melainkan wajib hadir secara penuh melalui pembiayaan APBN. Risiko fiskalnya nyata. Dana Siap Pakai (DSP), sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, tidak tunduk pada plafon anggaran daerah dan berpotensi mengganggu stabilitas APBN jika tidak direncanakan sejak awal. Dalam bahasa kebijakan publik, ini merupakan bentuk unbounded liability, tanggung jawab yang sulit diprediksi ujungnya.
Dalam nalar publik yang sederhana, kehati-hatian ini kerap dibaca sebagai persoalan keterbatasan ruang gerak anggaran. APBN dipersepsikan bukan sebagai tabungan cair yang dapat digunakan kapan saja, melainkan sebagai struktur belanja yang sebagian besar telah terkunci sejak awal tahun. Penetapan status Bencana Nasional dipahami akan memaksa negara membongkar prioritas yang telah disepakati, dengan segala konsekuensi administratif dan politiknya. Kekhawatiran serupa juga muncul pada fase pascabencana. Bantuan darurat mungkin dapat ditangani, tetapi rehabilitasi dan rekonstruksi dipandang sebagai komitmen jangka panjang yang sulit diukur batasnya sejak awal. Dalam pembacaan awam, di sinilah negara seolah memilih menahan eskalasi status demi menjaga keseimbangan fiskal dan stabilitas kebijakan.
Namun justifikasi tersebut tidak lagi relevan ketika bencana telah bertransformasi menjadi persoalan hak asasi manusia. Pada titik ini, argumen kehati-hatian fiskal tidak lagi memadai. Dalam kerangka tripartite obligation, kewajiban negara untuk menghormati (respect), melindungi (protect), dan memenuhi (fulfil) hak-hak warga seketika hadir, karena bencana merupakan situasi darurat HAM. Hak atas hidup, kesehatan, tempat tinggal, air bersih, dan lingkungan yang layak berada dalam posisi paling rentan. Negara tidak boleh menunda pemenuhan hak-hak tersebut hanya karena khawatir terhadap konsekuensi politik atau hukum yang mungkin muncul.
Justru di sinilah jebakan normatifnya. Penetapan status Bencana Nasional memang dapat dibaca sebagai pengakuan implisit atas kegagalan negara dalam pencegahan, terutama jika bencana memiliki unsur antropogenik seperti kebakaran hutan, deforestasi, atau tata kelola lingkungan yang buruk. Konsep strict liability menjadi relevan, dan posisi penggugat dalam citizen lawsuit dapat menguat. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 secara eksplisit membuka ruang gugatan terhadap pemerintah apabila lalai memenuhi hak-hak pengungsi. Namun dalam perspektif HAM, risiko dimintai pertanggungjawaban hukum bukanlah alasan sah untuk menunda atau mengecilkan respons negara. Negara digugat bukan karena bertindak terlalu cepat, melainkan karena lalai dan membiarkan warganya menanggung dampak bencana tanpa perlindungan yang memadai.
Menolong lebih dahulu, bahkan dalam kondisi ketidakpastian fiskal dan hukum, justru merupakan perwujudan kewajiban fulfil. Sebaliknya, menahan respons demi menghindari gugatan atau pengakuan kegagalan berisiko melanggar kewajiban respect dan protect. Negara yang takut “dimarahi” warganya lalu memilih tidak segera bertindak, pada dasarnya sedang membalik logika negara hukum: kepentingan perlindungan diri ditempatkan di atas perlindungan manusia.
Pemerintah juga kerap berdalih pada persoalan preseden dan potensi moral hazard. Indikator penetapan status bencana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 memang bersifat kualitatif, tanpa ambang batas yang tegas. Kekhawatiran bahwa satu penetapan akan memicu tuntutan serupa dari daerah lain sering dijadikan alasan untuk menahan keputusan. Namun logika ini bermasalah secara etis. Risiko tuntutan politik tidak boleh mengalahkan kewajiban konstitusional negara untuk melindungi warga dalam situasi darurat.
Demikian pula dengan alasan menjaga narasi pembangunan dan stabilitas nasional. Dalam perspektif ketahanan nasional, bencana kerap dipandang sebagai ancaman nonmiliter yang dapat mengganggu kepercayaan investor dan iklim bisnis. Namun ketika stabilitas ekonomi dijadikan alasan untuk menunda pengakuan penderitaan warga, negara sedang mengorbankan prinsip HAM demi citra pembangunan. Padahal legitimasi negara hukum tidak diukur dari seberapa stabil angka-angka makroekonomi, melainkan dari seberapa cepat dan adil negara hadir ketika warganya berada dalam kondisi paling rentan.
Dengan demikian, penetapan status Bencana Nasional seharusnya tidak diperlakukan sebagai beban politik yang dihindari, melainkan sebagai instrumen tanggung jawab negara. Keraguan negara untuk mengakui krisis justru memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar yaitu desain hukum kebencanaan kita masih memberi ruang bagi negara untuk menunda tanggung jawab atas nama kehati-hatian. Lebih menukik lagi, kita dapat mempertanyakan apakah desain hukum kebencanaan saat ini benar-benar memusatkan perlindungan kepada warga, atau justru menyediakan ruang aman bagi negara untuk menunda tanggung jawabnya. Dalam negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan menghormati HAM, kehati-hatian fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk mendahulukan keselamatan anggaran di atas keselamatan manusia.(*)
JANI PURNAWANTY
Mahasiswa Program Doktor Hukum & Pembangunan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Board Member Women & Youth Development Institute of Indonesia (WYDII)



