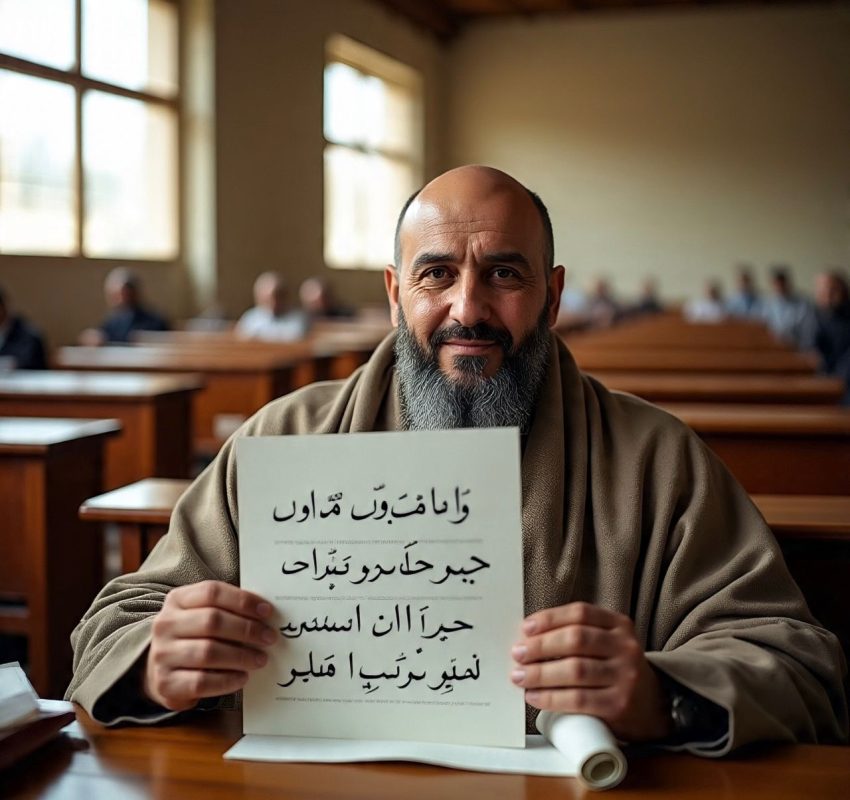
“Semua demokrasi menuntut pendidikan publik yang umum karena tidak ada yang membuat orang begitu mirip selain pendidikan yang sama.“
-Karl Jaspers (1883-1969) dalam Die Idee der Universität (1946)-
Ijazah, bahasa Arab ijāzah (إجازة) yang secara etimologis berarti izin, otorisasi, atau pemberian hak, yang dalam tradisi Islam klasik berarti izin atau otorisasi intelektual, pernah menjadi simbol kepercayaan antara guru dan murid.
Pada abad ke-9 hingga ke-12, seorang ulama memberikan ijazah al-tadris sebagai tanda bahwa muridnya telah layak mengajar atau meriwayatkan ilmu. Ijazah bukan sekadar kertas, melainkan pengakuan atas martabat intelektual. Atau, seorang guru atau ulama memberikan ijāzah al-tadrīs (izin mengajar) atau ijāzah al-riwāyah (izin meriwayatkan hadis).
Sejarah kemudian bergeser ke Eropa, di Universitas Bologna pada akhir abad ke-12, ketika gelar Doktor Hukum Perdata pertama kali dianugerahkan. Universitas Paris menyusul dengan gelar Master, dan sejak itu ijazah (licentia docendi) menjadi dokumen formal yang menandai kelulusan akademis.
Namun, dalam dunia pendidikan mutakhir, ijazah telah mengalami patologi yakni ia tidak lagi sekadar tanda otoritas keilmuan, melainkan menjadi objek politik, alat legitimasi kekuasaan, bahkan senjata untuk menjerat lawan. Kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ketujuh Joko Widodo (62) dan putranya Gibran Rakabuming Raka (37) adalah contoh paling mutakhir dari bagaimana ijazah berubah menjadi arena konflik.
Tuduhan itu bukan hanya menyerang individu, melainkan merusak fondasi kepercayaan terhadap seluruh sistem pendidikan. Ijazah yang seharusnya menjadi simbol kejujuran intelektual kini diperlakukan seperti komoditas yang bisa dipalsukan, dipertanyakan, atau dipakai sebagai alat politik.
Mortimer J. Adler (1902- 2001) dalam Paideia Proposal (1982) menuliskan, “Tujuan dari sekolah bukanlah pemberian ijazah, tetapi pengembangan pikiran.” Adler menegaskan bahwa fungsi pendidikan bukan sekadar menghasilkan ijazah, melainkan membentuk kemampuan berpikir kritis dan integritas intelektual. Bahkan menyinggung bagaimana simbol-simbol pendidikan bisa runtuh ketika otoritas moral hilang.
Selain itu, George A. Makdisi (1920-2002), profesor studi Arab dan Islam, terutama di Harvard University (1959–1973) dan University of Pennsylvania (1973–1990) dalam The Rise of Humanism in Classical Islam and the Christian World (2000; 2005) menunjukkan bahwa tradisi ijazah lahir dari kebutuhan menjaga integritas ilmu atau dalam istilahnya Imla (إملاء) atau dictation (Inggris); harafiah mencatat atau mengeja, bukan sekadar administrasi.
Ketika integritas itu hilang, ijazah menjadi kosong, hanya lembaran kertas tanpa makna. Karena itu, Maksidi menulis, “Ijazah bukanlah ijazah dalam pengertian modern, tetapi lisensi untuk mengajar, yang diberikan oleh seorang guru kepada seorang murid.“
Inilah krisis fundamental pedagogi mutakhir dimana pendidikan kehilangan ruhnya, dan ijazah kehilangan otoritasnya.
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie (69), Ketua Mahkamah Konstitusi pertama (2003–2008), Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (2012–2017), anggota Dewan Pertimbangan Presiden (2010), serta anggota Dewan Perwakilan Daerah (2019–2024), pernah menekankan bahwa tuduhan hukum atas ijazah palsu harus dilihat dari perspektif filsafat hukum.
Hukum tidak boleh berhenti pada prosedur formal, melainkan harus menimbang substansi keadilan. Jika tuduhan ijazah palsu dijadikan senjata politik, maka hukum telah kehilangan fungsinya sebagai pelindung kebenaran. Ia berubah menjadi labirin Kafkaesque, di mana prosedur lebih penting daripada substansi, dan kebenaran dikorbankan demi kepentingan kekuasaan.
Patologi ijazah adalah gejala dari runtuhnya hukum publik. Ijazah yang dulunya lahir dari otorisasi intelektual kini menjadi alat legitimasi politik. Pendidikan yang seharusnya membentuk manusia berpengetahuan justru menjadi panggung sandiwara. Tuduhan terhadap Jokowi dan Gibran, benar atau tidak, telah mendisrupsi seluruh sendi dunia pendidikan, karena ia menanamkan keraguan terhadap simbol akademis yang paling mendasar.
Sejarah mengajarkan bahwa ijazah adalah janji antara guru dan murid, antara ilmu dan integritas. Ketika janji itu dilanggar, maka runtuhlah kepercayaan publik. Patologi ijazah bukan sekadar soal dokumen palsu, melainkan soal hancurnya fondasi moral pendidikan. Dan ketika pendidikan kehilangan moral, maka hukum publik pun ikut runtuh, meninggalkan kita semua berdiri di depan pintu yang tak pernah terbuka.
#coverlagu: Lagu Rahmatun Lil’Alameen karya Maher Zain(44) dirilis pada 19–20 April 2022. Maknanya adalah “Rahmat bagi semesta alam”, sebuah pujian kepada Nabi Muhammad SAW yang digambarkan sebagai sosok pembawa kedamaian, kebaikan, dan petunjuk bagi umat manusia.
REINER EMYOT OINTOE (ReO)
Fiksiwan



