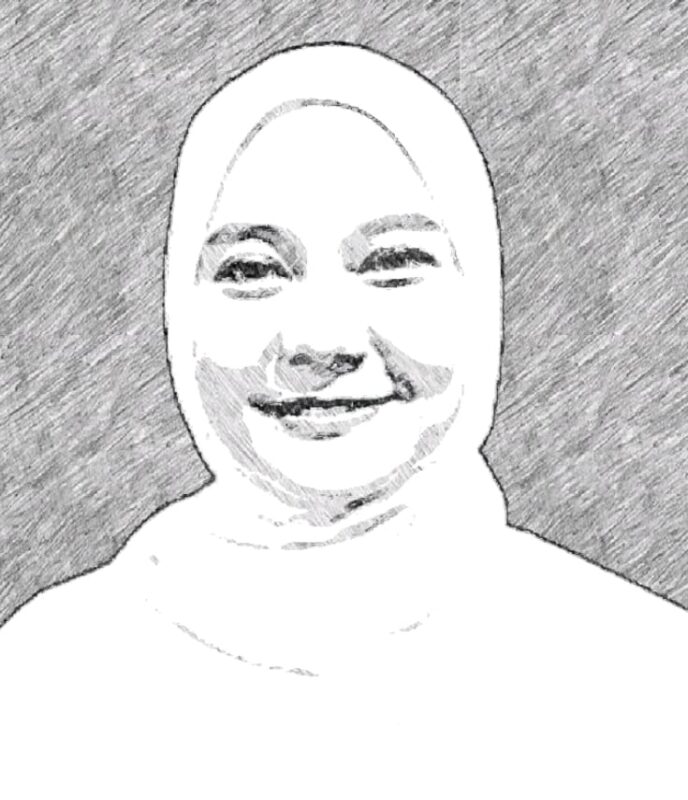
Indonesia merupakan negeri yang dikaruniai lanskap megah, terdapat gunung, laut, sungai, dan hutan. Namun sekaligus dilingkari bahaya yang terus berulang. Sejarah mencatat bencana besar yang meninggalkan luka panjang. Bencana tsunami Aceh 2004, gempa, tsunami dan likuifaksi Palu 2018, hingga banjir dan longsor masif di Sumatera pada 2025. Ketiganya bukan sekadar deretan angka korban atau kerusakan infrastruktur, tetapi potret kerentanan kita yang sesungguhnya. Bencana selalu menjadi cermin. Ia memperlihatkan bagaimana negara membangun ruang, bagaimana masyarakat memaknai alam, serta bagaimana budaya mengikat atau justru melepaskan hubungan manusia dengan lingkungannya.
Mari kita kembali menelisik pada 21 tahun yang lalu. Gelombang raksasa yang menggulung Aceh pada 2004 mengubah arah sejarah Indonesia. Namun ironinya, wilayah yang paling selamat justru bukan yang memiliki teknologi canggih, melainkan yang mempertahankan memori budaya. Masyarakat Pulau Simeulue, misalnya, selamat berkat warisan pengetahuan smong yaitu peringatan turun-temurun tentang tanda-tanda tsunami. Di banyak kawasan pesisir lainnya, modernisasi yang cepat membuat masyarakat semakin jauh dari memori ekologis tersebut. Pengetahuan tentang tanda alam memudar seiring pergeseran pola hidup. Tragedi Aceh menjadi penegasan bahwa mitigasi tidak hanya membutuhkan instrumen teknologi, tetapi juga revitalisasi pengetahuan lokal yang selama ini berfungsi sebagai sistem peringatan alami. Inilah inti pendekatan eko-kultural, dimana bencana lebih mudah dihadapi ketika budaya dan ekologi berjalan beriringan.
Berselang 14 tahun kemudian, alam kembali menampakkan kegagahannya. Kali ini tragedi yang maha dahsyat tersebut terjadi di Kota Palu. Kota ini tumbuh di atas lembah yang cantik, namun berdiri tepat di jalur sesar aktif. Ledakan gempa 7,5 magnitudo memicu tsunami lokal dan fenomena likuefaksi yang menelan permukiman secara tiba-tiba. Secara ekologis, wilayah Petobo dan Balaroa sudah lama dikenal sebagai tanah yang jenuh air. Secara budaya, masyarakat Kaili memiliki pengetahuan kosmologis tentang dinamika tanah dan perubahan lanskap. Namun urbanisasi yang masif mengalihkan orientasi pembangunan. Tanah dianggap sebagai ruang hunian, bukan sistem ekologis yang harus dihormati.Palu memperlihatkan bagaimana bencana lahir bukan hanya dari gesekan lempeng, tetapi juga dari tata ruang yang tidak memerhatikan geologi dan memori lokal. Ketika budaya kehilangan peran sebagai penuntun dalam membaca alam, kota menjadi rapuh.
Beberapa hari yang lalu, terjadi tanah longsor dan banjir bandang di beberapa bagian Pulau Sumatera. Contoh paling jelas bahwa kerusakan ekologis memperbesar risiko bencana hidrometeorologi. Hutan yang hilang, lereng yang tergerus, hingga daerah aliran sungai yang terfragmentasi membuat kawasan hulu kehilangan fungsinya sebagai penahan air. Mirisnya lagi, bahkan orang-orang yang dianggap bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, seolah tidak tahu-menahu tentang apa yang terjadi. Seolah telah melakukan banyak hal untuk mencegah terjadinya pembabatan hutan secara brutal, namun yang terjadi seolah tidak menggambarkan progress apapun.
Berbicara tentang dampak dari pembabatan hutan secara ugal-ugalan, maka komunitas adat yang akan merasakan dampak tersebut secara nyata. Dibanyak komunitas adat Sumatera, hutan dahulu dianggap sebagai ruang sakral dan dijaga melalui aturan adat. Namun ekspansi perkebunan skala besar dan pembukaan lahan yang serampangan memutus ikatan ekologis itu. Bencana pun lahir dari pertemuan antara curah hujan ekstrem dan degradasi jangka panjang yang dibiarkan. Peristiwa ini menandai bahwa bencana modern tidak lagi “alamiah sepenuhnya”, tetapi hasil intervensi manusia terhadap ekosistem yang melebihi daya dukungnya. Jika ketiga bencana tersebut disandingkan, terlihat pola yang konsisten dimana ruang dibangun tanpa membaca karakter ekologinya; adanya memori budaya tentang mitigasi yang perlahan hilang; modernisasi menekan tradisi yang sebenarnya berfungsi sebagai sistem keselamatan; serta kebijakan ruang lebih tunduk pada kepentingan ekonomi dibanding keselamatan jangka panjang.
Dengan kata lain, bencana terjadi pada titik ketika relasi manusia dengan lingkungan kehilangan keseimbangan. Pendekatan eko-kultural membantu menunjukkan bahwa persoalan kita bukan sekadar minimnya teknologi, tetapi pudarnya nilai yang dahulu mengatur cara manusia memperlakukan alam.
Jika Indonesia ingin membangun ketangguhan bencana, fondasinya harus berlapis dimana pertama, memperkuat perencanaan ruang berbasis risiko ekologis. Peta sesar, potensi likuefaksi, alur banjir, hingga zona tsunami harus menjadi dasar absolut sebelum izin pembangunan diterbitkan. Kedua, memulihkan nilai budaya yang menekankan keseimbangan. Narasi seperti smong, pamali, atau aturan adat hutan bukan romantisme masa lalu, tetapi pengetahuan ekologis yang efektif dan terbukti menyelamatkan. Ketiga, memulihkan ekosistem penyangga. Restorasi hutan, rehabilitasi DAS, dan perlindungan mangrove adalah bagian dari mitigasi struktural yang tidak bisa ditunda. Keempat, mempererat kolaborasi negara-ilmuwan-komunitas. Mitigasi bencana bukan ranah satu lembaga, tetapi kerja bersama yang memadukan data ilmiah dengan ingatan lokal masyarakat.
Bencana di Indonesia selalu menyisakan duka, tetapi juga membawa pesan moral. Alam bukan musuh, tetapi mitra yang selalu merespons cara kita memperlakukannya. Ketika memori ekologis dan budaya dihormati, bencana dapat diminimalkan. Namun ketika keduanya diabaikan, kerentanan menjadi konsekuensi yang tak terelakkan. Pendekatan eko-kultural mengajarkan bahwa ketangguhan bangsa tidak hanya dibangun oleh infrastruktur, tetapi juga oleh nilai, kebijakan, dan cara sebuah komunitas memaknai ruang hidupnya. Indonesia akan tetap menghadapi gempa, tsunami, dan banjir. Namun jika kita mampu merawat hubungan ekologis dan budaya, maka bencana tidak lagi menjadi siklus nestapa, tetapi titik tolak menuju peradaban yang lebih dewasa dalam memahami alam. Semoga.
RISMA ARIYANI
Mahasiswa Program Doktoral FISIP Universitas Airlangga



