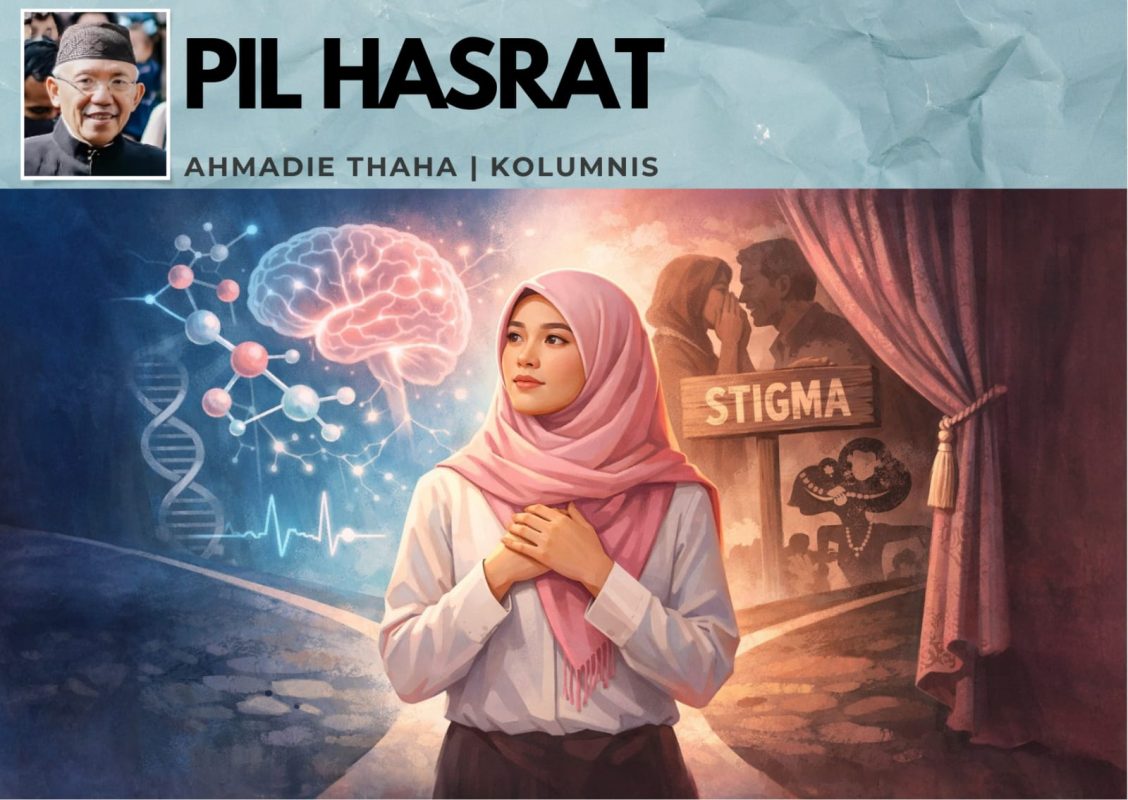
Konon, dalam kamus besar kehidupan modern, ada satu bab yang ditulis dengan tinta tipis dan dibaca sambil lalu yakni seksualitas perempuan. Bab itu biasanya ditutup rapat begitu perempuan memasuki menopause, seolah libido ikut pensiun dini, mengajukan surat berhenti bekerja, lalu dimakamkan secara administratif.
“Wajar,” kata banyak orang. “Hormon turun,” tambah yang lain, sambil menepuk bahu dengan empati palsu. Terutama hormon estrogen dan progesteron memang menurun drastis saat perempuan menopause; disusul perubahan pada testosteron yang juga ikut menurun, meski lebih perlahan. Seolah seks kemudian selesai. Lampu dimatikan. Tirai ditutup.
Padahal di ruangan sebelah, ketika seorang lelaki mengalami gangguan ereksi, sirene medis meraung, laboratorium sibuk, FDA berlari kecil, dan dunia farmasi seperti dikejar tenggat kiamat. Maka dalam enam bulan saja, viagra disahkan oleh FDA. Sejarah pun mencatat bahwa hasrat seksual lelaki adalah urusan peradaban; hasrat seksual perempuan, sekadar urusan perasaan.
Di sinilah absurditas itu mulai terasa. Seks, sejak Nabi Adam as, hingga algoritma Tinder, tidak pernah bersifat tunggal. Ia selalu duet, kadang sampai berlima kalau istri empat, tapi tidak pernah solo. Tak ada seks jika hanya satu pihak berhasrat sementara yang lain dianggap “sudah seharusnya begitu.”
Maka ketika penurunan hasrat seksual perempuan diperlakukan sebagai keniscayaan biologis tanpa solusi serius, sesungguhnya yang sedang kita saksikan bukan ilmu kedokteran, melainkan politik tubuh yang timpang. Tubuh lelaki diperlakukan sebagai mesin yang harus selalu siap hidup. Tubuh perempuan dianggap alamiah untuk aus, pelan-pelan, dan diterima dengan ikhlas.
Dalam terminologi medis, kondisi itu bukan dongeng feminis yang terlalu sensitif. Ia punya nama resmi yang dingin dan panjang yaitu hypoactive sexual desire disorder, atau HSDD. Gangguan hasrat seksual hipoaktif ini pertama kali dikarakterisasi secara klinis pada tahun 1977, jauh sebelum dunia ribut soal “female Viagra.”
HSDD merujuk pada kondisi menurunnya atau hilangnya hasrat seksual secara persisten, yang menimbulkan distress personal dan problem relasional, dan tak dapat dijelaskan semata-mata oleh kondisi medis lain, obat-obatan, atau masalah relasi. Dengan kata lain, ini bukan soal “kurang romantis” atau “kebanyakan mikir,” tapi sebuah kondisi neurobiologis yang nyata.
Ironisnya, meski sudah dipahami sejak era disko dan celana cutbray, HSDD lama dibiarkan mengendap di laci pengetahuan medis, tertutup rapat oleh selimut moral dan bias budaya. Dunia kedokteran, yang konon objektif dan rasional, ikut terjangkit keyakinan sosial bahwa hasrat perempuan itu opsional. Kalau ada, syukur. Kalau tidak ada, ya sudah.
Baru pada 2015, hampir empat dekade setelah HSDD dikenali, FDA Amerika Serikat menyetujui flibanserin. Ini adalah obat resep untuk mengatasi penurunan hasrat seksual pada perempuan yang bekerja di otak, dengan menyeimbangkan neurotransmiter seperti dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Jadi, bukan hormon dan bukan perangsang instan.
Nama obatnya Addyi. Enam tahun proses persetujuannya, setelah uji klinis melibatkan sekitar 13.000 perempuan. Ini tiga kali lipat lebih banyak dibanding uji viagra, namun obat ini tetap disambut dengan kecurigaan berlapis. Seakan-akan dunia berkata, “Kami tahu ini ilmiah, tapi apakah ini pantas?”
Di Indonesia, nama Addyi (flibanserin) nyaris tak terdengar di ruang praktik medis arus utama. Obat ini belum terdaftar secara resmi di BPOM dan tidak tersedia di apotek sebagai terapi medis yang diakui untuk penurunan hasrat seksual perempuan. Kalaupun mungkin namanya sesekali muncul di etalase daring atau percakapan forum kesehatan, itu sebatas diskusi saja.
Di negeri ini, pembicaraan soal libido perempuan masih lebih sering diparkir di wilayah “curhat”, “rumah tangga”, atau “kurang komunikasi”, bukan sebagai isu medis berbasis sains. Akibatnya, problem biologis-neurologis yang nyata sering larut dalam nasihat moral dan spiritual yang baik niatnya, tetapi tidak selalu tepat sasaran.
Hingga kini belum ada obat generik yang diakui secara medis untuk HSDD perempuan, baik di Indonesia maupun di banyak negara lain. Selain Addyi, secara global sebenarnya ada bremelanotide (Vyleesi), obat suntik yang disetujui FDA untuk HSDD pada perempuan pra menopause, namun nasibnya di Indonesia kurang lebih sama alias belum hadir secara resmi.
Yang lebih lazim dijumpai di sini justru suplemen “penambah gairah” berbahan herbal dengan klaim bombastis, tanpa dasar uji klinis yang kuat. Praktik medis yang relatif tersedia masih berkisar pada terapi hormon, konseling, atau pendekatan psikologis, yang tentu penting, tetapi belum menyentuh akar persoalan neurobiologis.
Di titik inilah Indonesia, bahkan dunia, masih tertinggal satu bab bahwa ketika sains sudah bicara, kebijakan dan budaya kita belum sepenuhnya mau mendengar. Dunia memang lama tak siap menghadapi gagasan bahwa perempuan punya hak atas hasratnya sendiri.
Padahal, obat seperti flibanserin bukan obat hormon, bukan afrodisiak instan yang bekerja seperti saklar lampu. Ia bekerja di otak, menyeimbangkan neurotransmiter seperti dopamin, norepinefrin, dan serotonin.
Secara sederhana, ia memperkuat sinyal hasrat dan meredam rem biologis yang terlalu keras. Mekanismenya lebih mirip pengaturan ulang orkestra saraf, bukan pemompaan darah ke organ tertentu. Ia diminum setiap hari, bukan menjelang “acara khusus,” seolah menegaskan bahwa hasrat bukan momen, tapi keadaan batin yang berkelanjutan.
Namun cerita belum selesai. Perempuan pasca menopause, kelompok yang justru paling sering mengalami perubahan libido, harus menunggu lebih lama lagi. Baru pada Desember 2024, FDA akhirnya memperluas persetujuan Addyi untuk digunakan perempuan pasca menopause di bawah usia 65 tahun yang jumlahnya jutaan.
Bukan karena molekulnya berbeda, bukan karena dosisnya berubah, melainkan karena FDA meminta peninjauan ulang data yang sejatinya sudah ada sejak awal. Cindy Eckert, CEO Sprout Pharmaceuticals yang membuat Addyi, menyebutnya apa adanya alias standar ganda. Dunia medis, katanya, begitu berhati-hati ketika menyangkut kesenangan perempuan.
Perlakuan FDA jauh lebih santai ketika membahas performa lelaki. Bandingkan saja. Ketika Viagra hadir, perdebatan publik lebih banyak berkisar pada lelucon larut malam dan iklan yang ceria. Sementara ketika Addyi muncul, yang dibahas pertama-tama adalah risikonya yaitu pusing, kantuk, mual, dan hubungan dengan alkohol.
Padahal angka penghentian obat flibanserin karena efek samping seperti pusing, kantuk, mual, dan hal-hal lain terkait alkohol, kurang dari dua persen. Anehnya, risiko itu terus diulang, seperti mantra, seolah tugas utama jurnalisme kesehatan adalah mengingatkan perempuan agar tidak terlalu berharap.
Di sinilah persoalan menjadi filosofis, terutama soal keadilan seksual yang tak lewat juga diingatkan Kitab Suci. Kita hidup dalam budaya yang cenderung menganggap perempuan sebagai makhluk psikologis yang emosional, subjektif, mudah cemas, sementara lelaki dipahami sebagai makhluk biologis yang rusakannya harus segera diperbaiki.
Bias ini muncul di mana-mana yakni diagnosis serangan jantung perempuan yang terlambat, pemberian analgesik yang lebih lambat, hingga cara kita memandang menopause sebagai “fase” alih-alih fenomena biologis kompleks. Hasrat seksual perempuan pun ikut direduksi menjadi urusan mental, bukan kesehatan.
Padahal, secara global, prevalensi disfungsi seksual justru lebih tinggi pada perempuan dibanding lelaki. Data studi epidemiologis besar, antara lain WHO Reports, menunjukkan sekitar 40-45% perempuan dewasa mengalami disfungsi seksual, dibanding 20-30% pada laki-laki, dengan penurunan hasrat sebagai keluhan paling umum pada perempuan.
Namun dana riset, inovasi farmasi, dan keberanian institusional lebih sering mengalir ke problem yang dianggap “penting”, sementara terkait penting bagi siapa, itu pertanyaan lain. Tak heran jika upaya menghadirkan pil hasrat untuk perempuan harus melalui jalan berliku, penuh debat moral, politik regulasi, dan sindiran sosial.
Akhirnya, pertanyaan kuncinya sederhana tapi mengganggu yaitu mengapa seks lelaki dianggap hak, sementara seks perempuan dianggap bonus?
Mengapa ketika perempuan kehilangan hasrat, solusinya relaksasi, tetapi ketika lelaki kehilangan ereksi, solusinya revolusi farmasi? Bukankah relasi seksual, secara definisi paling dasar, adalah ruang bersama antara lelaki dan perempuan, di mana ketimpangan hasrat berarti ketimpangan relasi?
Mungkin, seperti warna pink yang dipilih Cindy Eckert, yang dulu dianggap remeh dan kini dipakai sebagai simbol perlawanan, perjalanan Addyi adalah cermin perubahan budaya yang lambat tapi pasti.
Kita mesti mengakui bahwa hasrat perempuan bukan kelemahan, melainkan bagian dari vitalitas hidup. Bahwa menopause bukan garis akhir seksualitas, melainkan bab baru yang layak dipahami, diteliti, dan tentu perlu diobati.
Dan mungkin, di situlah pelajaran besarnya. Ketika sains akhirnya mengejar keadilan yang lama tertinggal, kita dipaksa bercermin bahwa bukan hanya soal pil dan neurotransmiter, tapi soal cara kita menghargai pengalaman tubuh manusia secara setara.
Seks, rupanya, bukan sekadar urusan ranjang, melainkan etika peradaban. Ketika satu pihak diabaikan, yang lumpuh bukan hanya hasrat, tapi juga kejujuran kita dalam mengaku diri sebagai masyarakat yang adil.
AHMADIE THAHA (Cak AT)
Wartawan Senior



